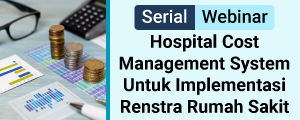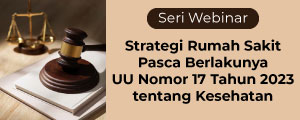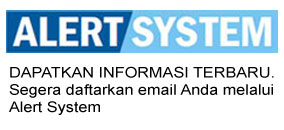–
–
Berikut ini adalah tanya jawab terkait dengan persiapan RSUD untuk menjadi BLUD, berisi rangkuman dari hasil workshop dan konsultasi yang dilakukan oleh PKMK FK UGM dengan beberapa RSUD di Indonesia. Saat membantu sebuat RSUD dalam persiapan menerapkan PPK BLUD, tim konsultan/fasilitator seringkali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan dari RSUD yang didasari pada kebutuhan untuk mempersiapkan diri dalam melakukan advokasi dengan Pemda dan DPRD.
1. Mengapa setelah menjadi BLUD, anggaran yang diperlukan oleh RSUD justru lebih banyak dibandingkan dengan sebelum BLUD?
Jawab:
Anggaran tersebut diperlukan untuk peningkatan pelayanan. Jika selama ini pelayanan RSUD mutunya dibawah SPM, maka pasti RSUD mendapat banyak komplain dari masyarakat. Bapak/ibu pejabat daerah juga enggan berobat ke RSUD, dan lebih memilih ke RS swasta atau ke luar daerah. Mengapa? Karena pelayanan di RSUD dianggap buruk, tidak bermutu, apalagi bergengsi. Jadi RSUD membutuhkan anggaran tersebut untuk mengangkat kualitas pelayanan minimal agar sesuai dengan SPM.
Menjadi BLUD bukan berarti kemudian RS menjadi sebagai mesin uang (bagi Pemda). BLUD berarti menjadikan RS lebih bermutu. Jika RS bermutu, masyarakat yang sakit akan lebih cepat sehat kembali. Jika mereka sehat, mereka akan lebih produktif, bisa kerja lebih banyak, bisa membayar pajak lebih banyak. Kalau mereka sakit lebih lama, mereka akan butuh subsidi lebih banyak. Pemda pilih mana?
2. Apa untungnya BLUD bagi Pemda kalau anggaran/subsidi untuk RSUD malah tambah banyak (dari proyeksi keuangan di RSB)?
Jawab:
Permendagri 61/2007 Pasal 1 ayat 1 berbunyi: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dilain pihak, BLUD atau tidak BLUD, RSUD memiliki misi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang miskin. Jadi sepanjang RS diwajibkan untuk melayani orang miskin maka sepanjang itulah subsidi dari pemerintah dibutuhkan. Karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan oleh RS. Jika sudah jadi BLUD, diharapkan RSUD akan menjadi lebih efisien. Jadi untungnya bagi Pemda adalah anggaran daerah bisa dimanfaatkan secara lebih baik, tidak bocor (inefisiensi), tidak salah alokasi (subsidi untuk pelayanan yang dinikmati oleh bukan orang miskin), dan masih banyak lagi.
3. Lalu dimana letak bedanya antara yang sudah BLUD dengan yang belum?
Jawab:
Bedanya: yang sudah BLUD diharapkan tarifnya sesuai dengan unit cost. Jadi kalau tarif pelayanan untuk orang miskin lebih rendah dari unit cost, disitulah subsidi pemerintah terjadi. Pelayanan Kelas III tentunya boleh-boleh saja disubsidi. Namun jangan sampai pelayanan Kelas VIP dan Kelas I yang disubsidi oleh Pemerintah. Artinya jangan sampai tarif di kelas-kelas pelayanan tersebut lebih rendah dari unit cost karena itu berarti APBD mensubsidi orang mampu.
4. Mengapa perlu ada insentif khusus/jasa layanan untuk tenaga yang bekerja di RS? Bukankan mereka sudah mendapat gaji?
Jawab:
Kita perlu memberi insentif tersebut karena profesionalisme, karena orang-orang yang bekerja di RS merupakan profesi-profesi yang khusus. Semakin langka suatu profesi, makin tinggi insentifnya. Dan itu berlaku dimanapun di seluruh dunia. Selain itu, terkait juga dengan masalah risiko pekerjaan. Orang yang bekerja di RS menghadapi berbagai risiko, mulai dari tertular penyakit pasien sampai risiko tuntutan kalau terjadi kesalahan. Ini perlu dilindungi, salah satunya dengan memberi insentif lebih. Kemudian terkait masalah kekhususan pekerjaan. Pelayanan di SKPD lain di daerah kebanyakan tidak buka 24 jam. Jadi Pk. 14.00 para karyawannya sudah bisa pulang dengan tenang dan besoknya baru melanjutkan pekerjaannya lagi. Orang yang bekerja di RS tidak bisa seperti itu. Meskipun yang shift pagi bisa pulang ke rumah pukul 14.00, tetap saja sewaktu-waktu mereka harus ready jika ada masalah di RS, entah dia itu manajemen, apalagi kalau dia adalah seorang dokter atau perawat.
Karena keterampilannya bersifat khusus, orang-orang yang bekerja di RS saat masih bersekolah menempuh pendidikan dengan perjuangan yang sangat tidak mudah. Maka wajar jika diberi insentif yang berbeda dengan SKPD lainnya.
Untuk mendapatkan tingkat profesionalisme seperti yang dimiliki oleh staf yang bekerja di RS sangat tidak mudah. Diperlukan pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu dan finansial yang tidak sedikit untuk menjadi profesi tertentu (misal dokter spesialis, perawat khusus, dan sebagainya). Pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di RS memiliki kompetensi yang memenuhi standar. Orang-orang yang datang ke RS dengan masalah kesehatan berarti menyerahkan “nasibnya” bahkan nyawanya pada tenaga kesehatan. Tentunya kita tidak ingin masyarakat ini kemudian dilayani oleh tenaga yang tidak kompeten.
5. Banyak kekhawatiran di kalangan pejabat Pemda, bahwa jika RSUD sudah dtetapkan menjadi BLUD maka tarifnya jadi mahal. Bagaimana menjelaskan hal ini?
Jawab:
Tarif naik atau tidak pasca BLUD, itu kembali pada kebijakan Pemda itu sendiri. Pemda bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua warganya bisa mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Jika ada warganya yang tidak mampu mengakses karena keterbatasan finansial, mana disitulah tanggung jawab Pemda untuk “membelikan” pelayanan tersebut bagi warganya yang tidak mampu dan itulah yang disebut sebagai subsidi. Untuk pelayanan di kelas-kelas lainnya, jika masih mendapat subsidi dari Pemda maka bisa saja tarifnya tidak naik atau naik sedikit, sesuai dengan selisih unit cost yang terjadi. Namun pertanyaannya adalah apakah wajar jika masyarakat yang mampu juga mendapat subsidi dari Pemda?
6. Apa saja yang harus berubah di RSUD jika telah ditetapkan sebagai BLUD?
Jawab:
Menjadi BLUD itu berarti mengubah budaya kerja. Bukan masalah uang saja, tapi mindset harus ikut berubah. Tadinya biasa dilayani, sekarang melayani. Tadinya “pasien butuh RS” sekarang “RS butuh pelanggan”. Tadinya uang disetor (ke Pemda), sekarang bisa dikelola sendiri (di rekening RSUD). Jika mindset tidak berubah, bisa dibayangkan bagaimana cara orang-orang RSUD mengelola uang yang sangat banyak tersebut.
7. Bukankan berubah menjadi BLUD prinsipnya hanya berubah dari “dulu setor, sekarang tidak”?
Jawab:
Tidak sesederhana itu. Dulu sebelum BLUD, mentalnya adalah mental “setoran” dan mental menghabiskan anggaran sebab jika anggaran tidak terserap/tidak habis, maka akan dianggap kinerjanya jelek. Sedangkan jika sudah BLUD, mentalnya kebalikan, yaitu harus berhemat, harus efisien. Jika ada dua barang yang satu seharga Rp 500 yang satubnya lagi seharga Rp 600 dengan mutu sama, mengapa harus membuang uang Rp 100 meskipun di anggaran sudah direncanakan Rp 600? Jadi tidak sesederhana “dulu setor sekarang tidak”. RS harus mulai berpikir enterpreneurship. Manajer RS dituntut untuk menjadi Manajer sungguhan, bukan sekedar Kepala RS, Kepala Keuangan, Kepala Perencanaan, Kepala Staf dan seterusnya, tapi sebagai manajer keuangan, manajer SDM, manajer operasional.
8. Banyak RS yang melaksanakan morning report. Sebenarnya morning report untuk apa? Dan berapa lama diperlukan waktu untuk melakukan morning report?
Jawab:
Morning report biasanya digunakan sebagai moment untuk berkomunikasi antara manajemen dengan fungsional sekaligus membahas berbagai masalah yang ada di RS dan menyepakati solusinya. Dari berbagai masalah yang di-morning-report-kan, baru bisa diketahui butuh berapa lama untuk melakukan morning report. Idealnya antara 30-60 menit jika dilakukan setiap hari. Jika hanya seminggu sekali, tentu lebih banyak waktu yang diperlukan karena masalah yang perlu dibahas sudah terakumulasi dalam seminggu.
Morning report ini juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengubah budaya organisasi. Jika pimpinan RS komitmen untuk melaksanakan morning report, harus on time. Misalnya saja semua sepakat MM dimulai Pk. 7.00. Jadi begitu waktu menunjukkan Pk. 7 MM harus dimulai, tidak perlu menunggu yang belum datang. Lama kelamaan yang biasa terlambat akan menyesuaikan diri. (Kebiasaan untuk datang terlambat ke sebuat pertemuan adalah karena pertemuan sering molor dari undangan.) Namun pimpinan harus memberi contoh. Pimpinan bukan hanya direktur tapi juga semua pejabat di RS. Semua atasan harus beri contoh pada bawahan masing-masing. Ini salah satu cara mengubah budaya organisasi. Jika ini berlangsung secara konsisten, maka komponen-komponen yang ada di dalam RS akan bisa kompak.
Semakin banyak staf RS yang paham tentang BLUD akan semakin baik, sebab nanti para pimpinan tidak terlalu susah menggerakkan orang-orangnya untuk mencapai tujuan bersama.
9. Mengapa permohonan RSUD untuk menjadi BLUD bisa ditolak? Bagaimana agar bisa lebih meyakinkan Pemda (dan DPRD)?
Jawab:
Jika syarat administratif (dari hasil penilaian BLUD oleh tim penilai) nilainya kurang dari 60, maka pasti harus ditolak. Namun ini masih bisa diperbaiki. RS harus melengkapi atau memperbaiki syarat administrasi tersebut sesuai dengan masukan dari tim penilai. Lalu kemudian dilakukan penilaian ulang. Jika penyebabnya bukan syarat administratif (misal karena politis) RS perlu gunakan pendekatan atau advokasi. Gunakan semua peraturan tentang BLUD dan semua referensi yang terkait sebagai amunisi. Untuk dapat menggunakannya sebagai amunisi, tentu harus menguasai dulu isi peraturan-peraturan tersebut, dan yang terpenting memahami prinsip BLUD. Jika semua peraturan sudah dibaca dan dikuasai, pasti bisa memberikan penjelasan yang logis dan berdasar kuat saat melakukan advokasi.
10. Apa contohnya bahwa RSUD akan lebih efisien jika sudah ditetapkan sebagai PPK BLUD?
Jawab:
Contoh dulu sebuah RSUD di Jawa Tengah membeli lift untuk pasien seharga Rp 400 juta dengan penunjukkan langsung. Jika belum BLUD, pengadaan dengan harga setinggi itu harus melalui lelang. Harga lift ditambah dengan biaya lelang dan sebagainya, maka anggaran yang dibutuhkan kira-kira menjadi Rp 600 juta. Dalam hal ini BLUD menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp 200 juta. Ini baru dari pengadaan lift.
Contoh lain, BLUD menetapkan tarif berdasarkan unit cost. Jika tarif Kelas III lebih rendah dari unit cost, maka selisihnya disubsidi oleh pemda. Sedangkan tarif Kelas VIP dan Kelas I tidak boleh lebih kecil dari unit cost (diatur oleh Perbup). Dan karena ditetapkan dengan Perbup, maka tarif VIP dan Kelas I bisa dibuat menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga, agar tidak dibawah unit cost. Jika tarif Kelas VIP masih dibawah unit cost (karena ditetapkan melalui Perda yang sulit diubah) siapa yang akan menanggung selisihnya? Secara tidak disadari, selisih ini ditutupi oleh APBD. Artinya APBD diserap oleh orang kaya. Dengan kata lain Pemda mensubsidi orang yang sebenarnya mampu membayar sendiri. Tentu saja ini jauh dari prinsip efisiensi.
Contoh lain lagi adalah di Perencanaan Tahunan. RBA bersifat fleksibel, jadi bisa mengikuti kebutuhan RS (pasien). Kalau tidak memerlukan suatu barang/jasa maka RS tidak perlu membeli, meskipun saat merencanakan hal tersebut dianggarkan. Jika perlu dan kurang, RS bisa menambah anggaran, meskipun saat perencanaan hal tersebut anggarannya kurang dibandingkan dengan kebutuhan saat implementasi. Dengan cara ini pasti RS menjadi jauh lebih efisien dibandingkan “butuh nggak butuh tetap beli, dan jika tidak terpakai barang akan numpuk di gudang sampai expired”.
Dalam hal kepegawaian, jika kompetensi seorang karyawan tidak pas dengan kebutuhan RS (apalagi jika perilakunya juga tidak sesuai dengan budaya kerja yang ingin dikembangkan), bisa saja dikembalikan staf tersebut ke pemda dengan alasan kinerja (karena BLUD punya ukuran kinerja). Atau diberhentikan (kalau pegawai yang bersangkutan diangkat oleh BLUD) dan RS bisa merekrut staf baru yang lebih sesuai. Tentunya ini akan lebih menghemat anggaran RS/Pemda dibandingkan dengan “mempekerjakan orang yang hanya makan gaji buta namun kinerjanya tidak jelas”.
Tulisan terkait:
Pertanyaan seputar BLUD
 Liputan6.com, Jakarta : Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dipopulerkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memungkinkan warga tak mampu untuk tidak dipungut biaya saat berobat di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan darah? Sebab, hingga kini masyarakat masih dibebani sejumlah uang untuk mendapatkan darah saat membutuhkan.
Liputan6.com, Jakarta : Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dipopulerkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memungkinkan warga tak mampu untuk tidak dipungut biaya saat berobat di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan darah? Sebab, hingga kini masyarakat masih dibebani sejumlah uang untuk mendapatkan darah saat membutuhkan.





 Jakarta : Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit di Indonesia masih jauh dari kata bagus. Sakit buruknya, masyarakat bisa diibaratkan masuk ke hutan belantara saat ke rumah sakit.
Jakarta : Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit di Indonesia masih jauh dari kata bagus. Sakit buruknya, masyarakat bisa diibaratkan masuk ke hutan belantara saat ke rumah sakit. Jakarta, PKMK. Manajemen rumah sakit di Indonesia sekarang ini semakin lengkap dalam mengaplikasikan software (perangkat lunak) teknologi informasi. Di kalangan RS sudah ada yang mengembangkan sendiri software tersebut. Serta ada juga yang membeli paket software yang terintegrasi front to end solutions keluaran vendor terkemuka, ungkap Goenawan Loekito, Pemerhati teknologi informasi di Jakarta (12/4/2013).
Jakarta, PKMK. Manajemen rumah sakit di Indonesia sekarang ini semakin lengkap dalam mengaplikasikan software (perangkat lunak) teknologi informasi. Di kalangan RS sudah ada yang mengembangkan sendiri software tersebut. Serta ada juga yang membeli paket software yang terintegrasi front to end solutions keluaran vendor terkemuka, ungkap Goenawan Loekito, Pemerhati teknologi informasi di Jakarta (12/4/2013). Surabaya – Sebanyak 80 delegasi dari beberapa Negara yang ikut Forum SOM II “Asia-Pacific Economic Cooperation” (APEC) mengunjungi pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Soetomo Surabaya, Kamis (11/04/2013) sore.
Surabaya – Sebanyak 80 delegasi dari beberapa Negara yang ikut Forum SOM II “Asia-Pacific Economic Cooperation” (APEC) mengunjungi pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Soetomo Surabaya, Kamis (11/04/2013) sore.