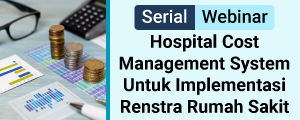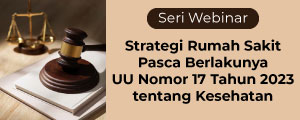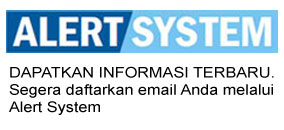Dampak Tekanan Berbagai Pihak terhadap Pelayanan di Rumah Sakit di Era BPJS
Swiss Belhotel, 3 – 6 September 2013
Putu Eka Andayani[i]
Hari 1: Seminar Pra-Munas
Selasa, 3 September 2013
 Sesi pertama seminar ini diisi dengan materi-materi yang terkait dengan pengaruh tekanan pemerintah, masyarakat dan media massa terhadap pelaksanaan etika dan keselamatan pasien.
Sesi pertama seminar ini diisi dengan materi-materi yang terkait dengan pengaruh tekanan pemerintah, masyarakat dan media massa terhadap pelaksanaan etika dan keselamatan pasien.
Pembicara pada sesi pertama seminar antara lain Prof. Dr. Herkutanto ((Ketua KKPRS) dan Dr. Priyo Sidi Pratomo, SpR (Ketua MKEK PB IDI).
Pada sesi ini, pembicara sangat mengapresiasi acara ini karena menempatkan etika sebagai tema pertama yang harus dibahas. Hal ini karena semua yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit harus berlandaskan pada etika. Pada diskusi juga dibahas mengenai biaya mutu dan tata kelola RS. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan hak setiap warna Negara. Jika RS menerapkan tata kelola yang baik, maka masyarakat miskin pun akan mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan yang bermutu.
 Dalam kaitannya dengan implementasi tarif berdasarkan INA-DRGs, respon yang harus dilakukan oleh RS adalah mengkalkulasi setiap biaya. Akan terjadi pergeseran jika pada mekanisme fee for service terjadi hubungan yang fokus pada dokter-pasien, dengan universal coverage hubungan ini akan bergeser ke RS-dokter, RS-pasien dan RS-media massa. Jadi RS yang akan melakukan kredensial terhadap dokter mana saja yang boleh direkrut untuk bekerja di RS tersebut. Jika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab (di pengadilan) adalah RS, bukan dokter. Di AS, pasien tidak boleh memilih dokter melainkan memilih RS.
Dalam kaitannya dengan implementasi tarif berdasarkan INA-DRGs, respon yang harus dilakukan oleh RS adalah mengkalkulasi setiap biaya. Akan terjadi pergeseran jika pada mekanisme fee for service terjadi hubungan yang fokus pada dokter-pasien, dengan universal coverage hubungan ini akan bergeser ke RS-dokter, RS-pasien dan RS-media massa. Jadi RS yang akan melakukan kredensial terhadap dokter mana saja yang boleh direkrut untuk bekerja di RS tersebut. Jika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab (di pengadilan) adalah RS, bukan dokter. Di AS, pasien tidak boleh memilih dokter melainkan memilih RS.
Proteksi terhadap dokter disebut sebagai medical liability system. Ada negara yang menerapkan hukum dimana adverse event di RS merupakan beban negara. Hal ini misalnya terjadi di Perancis dan Swedia. Menurut para pembicara, Indonesia sudah mulai harus memikirkan hal tersebut, agar para tenaga kesehatan (dokter, perawat dan sebagainya (dapat bekerja dengan tenang tanpa terbebani oleh masalah-masalah hukum atau keharusan membuat incidence report.
Dilain pihak, biaya mutu menjadi sangat tinggi karena tingginya biaya mendatangkan pakar Patient Safety ke RS. Untuk mengatasi hal ini, Kemenkes akan mengadakan TOT Patient Safety untuk membuat upaya peningkatan patient safety menjadi lebih terjangkau.
Kesimpulan yang dapat ditulis dari sesi ini antara lain:
- Dalam menerapkan etika di RS, prinsip yang penting adalah pemahaman mengenai penjelasan UU RS mengenai hak dan kewajiban RS dan dokter. Pelayanan kesehatan di RS merupakan pelayanan oleh tim yang mengedepankan keadilan dan moral yang baik.
- Dokter memiliki peran penting untuk mencegah komplain pasien. Jadi upaya meningkatkan motivasi dokter bukan hanya dilihat dari aspek makro dan perlu upaya untuk mencegah terjadinya moral hazard.
- Implementasi kebijakan mengenai KTD harus dilakukan secara hati-hati, serta memerlukan adanya kolaborasi antara dokter dengan komite medis. Prinsipnya adalah menerapkan good clinical governance dan patient safety.
 Sesi kedua menghadirkan parapraktisi sebagai pembicara, antara lain ketua komite medis dan direktur RSUD Pasar Rebo Jakarta, serta kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Koja. Sesi ini mengangkat tema dampak tekanan masyarakat dan media massa tehadap pelaksana pelayanan kesehatan akibat kebijakan JKN, dilihat dari perspektif pelaksana.
Sesi kedua menghadirkan parapraktisi sebagai pembicara, antara lain ketua komite medis dan direktur RSUD Pasar Rebo Jakarta, serta kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Koja. Sesi ini mengangkat tema dampak tekanan masyarakat dan media massa tehadap pelaksana pelayanan kesehatan akibat kebijakan JKN, dilihat dari perspektif pelaksana.
Ketua Komite Medis RSUD Pasar Rebo Dr. Yudi Amiarno, SpU memaparkan hasil penelitiannya terhadap 73 orang dokter yang bekerja di RS. Menurut Dr. Yudi, dokter adalah profesi yang terikat sumpah. Bahkan IDI Jakarta Timur menerapkan kebijakan bagi setiap dokter yang akan memperpanjang ijin prakteknya untuk mengucapkan kembali sumpah dokter, dengan tujuan agar selalu teringat akan isi dan makna sumpah tersebut.
Di RSUD Pasar Rebo, Komite Medis memiliki kegiatan rutin untuk membahas morbiditas, mortalitas dan lain-lain, mulai dari pertemuan Reboan, pertemuan siang klinik, audit medis hingga diskusi ilmiah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sejak berlakunya program Kartu Jakarta Sehat pada November 2012, hampir 60% dokter mengaku semakin sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini karena semakin banyaknya jumlah pasien yang harus ditangani padahal jumlah tenaga tidak ditambah.
 Sebagai gambaran, kunjungan pasien rawat jalan sejak dilaksanakannya Program KJS meningkat hampir dua kali lipat. Sebanyak 63% dokter harus melayani lebih dari 100 pasien rawat jalan per hari dan 30% melayani 50-100 pasien per hari. Sebanyak 55% dokter menggunakan 5-6 menit waktu untuk bertemu pasien (anamnese dan sebagainya). Hanya 27% yang mengaku berbicara dengan pasien selama 30 menit. Padahal menurut Kepmenkes No. 81/2004, ada standar baku yang diatur untuk itu. Sebagai contoh, dokter spesialis penyakit dalam berdasarkan Kepmenkes tersebut harus menggunakan setidaknya 8 menit per pasien lama dan 9 menit per pasien baru di poliklinik. Alokasi waktu ini belum termasuk waktu untuk melakukan tindakan, misalnya pemasangan kateter. Ini menyebabkan 69% dokter merasa ada peningkatan beban kerja yang melebihi kewajaran dan 60% dokter merasa mudah lelah.
Sebagai gambaran, kunjungan pasien rawat jalan sejak dilaksanakannya Program KJS meningkat hampir dua kali lipat. Sebanyak 63% dokter harus melayani lebih dari 100 pasien rawat jalan per hari dan 30% melayani 50-100 pasien per hari. Sebanyak 55% dokter menggunakan 5-6 menit waktu untuk bertemu pasien (anamnese dan sebagainya). Hanya 27% yang mengaku berbicara dengan pasien selama 30 menit. Padahal menurut Kepmenkes No. 81/2004, ada standar baku yang diatur untuk itu. Sebagai contoh, dokter spesialis penyakit dalam berdasarkan Kepmenkes tersebut harus menggunakan setidaknya 8 menit per pasien lama dan 9 menit per pasien baru di poliklinik. Alokasi waktu ini belum termasuk waktu untuk melakukan tindakan, misalnya pemasangan kateter. Ini menyebabkan 69% dokter merasa ada peningkatan beban kerja yang melebihi kewajaran dan 60% dokter merasa mudah lelah.
Banyaknya kunjungan pasien menyebabkan masyarakat datang ke RS lebih pagi (pukul 4-5 pagi) untuk mendapatkan nomor antrian awal. Karena ada jeda waktu beberapa jam dengan jam buka pelayanan, pasien semakin menumpuk di ruang tunggu sehingga banyak yang lesehan di lantai karena tidak kebagian tempat duduk. Bahkan banyak yang membawa bekal untuk sarapan karena akan menunggu sangat lama. Dilain pihak, pertambahan bean kerja ini tidak berdampak pada peningkatan pendapatan dokter. Setidaknya, hal ini diakui oleh 60% responden yang terlibat dalam penelitian ini. Dampak lebih jauh, 70% dokter merasa mutu pelayanan menurun, dimana layanan disini diartikan sebagai layanan RS (antrian pendaftaran, obat, parkir dan lainnya) serta layanan klinis.
 Dr. Yuda menutup presentasinya dengan memaparkan harapan para dokter, bahwa program KJS perlu dilanjutkan (78%) karena jelas mendatangkan manfaat bagi masyarakat tidak mampu, namun harus dievaluasi terlebih dahulu (70%) khususnya mengenai tarif, kesejahteraan dokter, mutu yang harus dijaga, serta sistem rujukan.
Dr. Yuda menutup presentasinya dengan memaparkan harapan para dokter, bahwa program KJS perlu dilanjutkan (78%) karena jelas mendatangkan manfaat bagi masyarakat tidak mampu, namun harus dievaluasi terlebih dahulu (70%) khususnya mengenai tarif, kesejahteraan dokter, mutu yang harus dijaga, serta sistem rujukan.
Dari seluruh unit pelayanan di RS, Instalasi Gawat Darurat merupakan salah satu unit yang paling menunjukkan adanya peningkatan beban kerja secara kasat mata. Menurut Dr. Deddy, Kepala IGD RSUD Koja, sejak diterapkanny aprogram KJS ia menerima 150-200 pasien per hari. Untuk melayani pasien-pasien ini, IGD-nya diperkuat oleh 14 orang dokter umum, 30 perawat, 5 petugas entri, 1 petugas pos dan 14 orang petugas call center. IGD memiliki fasilitas OK cito, radiologi dan laboratorium.
Pada Januari 2011, terdapat 2400-an kunjungan pasien dan pada bulan Desember 2700-an. Pada tahun ini kunjungan terbanyak adalah 2900-an pasien sebulan. Pada tahun 2012 kunjungan tertinggi dalam satu bulan mencapai angka 4959 pasien.
Dampak tekanan pemerintah terhadap pelayanan di IGD menurut Dr. Deddy antara lain:
- RS menjadi sangat crowded karena tidak boleh menolak pasien.
- Pasien yang dirujuk menjadi tanggung jawab RS perujuk. Diakui bahwa ini memang adalah prosedur yang benar, sehingga RSUD Koja telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap, tanpa membebani keluarga pasien. Namun, jika rujukan tersebut dikirim ke RS swasta, RS penerima meminta kehadiran keluarga pasien dan ini sering menimbulkan komplain dari keluarga.
- Boleh menitipkan pasien ke kelas yang lebih tinggi jika kelas III telah penuh. Masalahnya adalah kapasitas kelas III sudah mencapai 400 TT dan sering penuh, sedangkan kelas II hanya30 TT.
- Pejabat sering menitipkan keluarga atau kerabatnya yang sakit dan minta didahulukan untuk mendapatkan kamar. Ini sering menyalahi aturan yang berlaku dimana priositas didasarkan pada indikasi medis.
- Ketua RT/RW sangat mudah memberikan KTP atau KK pada warga meskipun bukan warga DKI, sehingga jumlah “penikmat” program KJS semakin besar.
- Pasien sering meminta ruang langsung pada perawat. Bahkan awak media massa juga sering ikut mencarikan ruang bagi pasien.
Dr. Deddy menutup presentasinya dengan menyimpulkan bahwa tenaga kesehatan di IGD terganggu dengan adanya berbagai tekanan tersebut. Tidak jarang terjadi konflik antara petugas dengan pengunjung yang berakhir pada adu fisik. Untuk itu, saran yang diajukan adalah adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh pihak tersebut agar terjadi pengertian yang seimbang terhadap fungsi pelayanan dan pembiayaa.
 Pembicara selanjutnya yaitu Ahyar, SKep, NERS, MKes, yang memaparkan megenai dampak tekanan pemerintah dan media massa terhadap motivasi dan kinerja perawat. Senada dengan yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, tekanan yang muncul menyebabkan stress yang tinggi dan menurunkan motivasi serta kinerja perawat. Bahkan, pemberitaan yang tidak berimbang oleh media massa menimbulkan rasa trauma dalam melayani. Pemberitaan yang tidak imbang seringkali disebabkan oleh karena pasien tidak diberi hak sebagai pasien KJS karena tidak dapat melengkapi dokumen identitas sesuai prosedur dan kondisi kapasitas yang sudah penuh padahal ada kebijakan RS tidak boleh menolak pasien.
Pembicara selanjutnya yaitu Ahyar, SKep, NERS, MKes, yang memaparkan megenai dampak tekanan pemerintah dan media massa terhadap motivasi dan kinerja perawat. Senada dengan yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, tekanan yang muncul menyebabkan stress yang tinggi dan menurunkan motivasi serta kinerja perawat. Bahkan, pemberitaan yang tidak berimbang oleh media massa menimbulkan rasa trauma dalam melayani. Pemberitaan yang tidak imbang seringkali disebabkan oleh karena pasien tidak diberi hak sebagai pasien KJS karena tidak dapat melengkapi dokumen identitas sesuai prosedur dan kondisi kapasitas yang sudah penuh padahal ada kebijakan RS tidak boleh menolak pasien.
Banyak juga “calo” administrasi yang dimanfaatkan oleh keluarga pasien (32,02%) dan kemudian mengacaukan alur pelayanan. Untuk itu, perlu ada pengawasan yang ketat, termasuk dari pihak luar RS.
Dengan beban kerja yang meningkat tersebut, angka kesakitan perawat menjadi lebih tinggi sehingga produktivitasnya menurun. Masalah lain yang dikemukakan adalah bahwa BPJS tidak mengakomodir perawat dalam kapitas, hanya dokter dan bidan.
Untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah maupun akan muncul, Dr. Trinovianti, MARS (Direktur RSUD Pasar Rebo) memaparkan bahwa RSUD PR telah membuat SPM dan SOP sampai dengan penulisan resep untuk obat generik atau obat terendah dan di-cross-check dengan DPHO. Hal ini karena saat itu manlak KJS belum ada. RSUD PR juga mengalami peningkatan jumlah pasien, dimana tahun 2011 ada 264.971 kunjungan pasien (24.923 diantaranya gakin) dan tahun 2012 meningkat meniadi 272.711 kunjungan (33.502 diantaranya gakin). Tahun 2013 hingga bulan Juli sudah terdapat 177.704 kunjungan (53.455 diantaranya gakin).
Jumlah kunjungan rawat inap juga tidak kalah fantastis. Tahun 2011 terdapat 16.811 kunjungan (2.439 diantaranya gakin), tahun 2012 terdapat 16.195 kunjungan (3.954 diantaranya KJS) dan 2013 (hingga Juli) terdapat 9.035 kunjungan (3.997 diantaranya KJS). Hal ini berdampak pada jam pelayanan yang menjadi lebih panjang, dimana jam buka poliklinik lebih panjang satu jam dan jam pelayanan farmasi lebih panjang 3,5 jam dari jam kerja resmi.
 Jumlah kunjungan pasien yang meningkat tidak diimbangi oleh penambahan jumlah SDM, sarana yang memadai serta ketersediaan tenaga pengganti (jika ada petugas yang sakit karena kelelahan).
Jumlah kunjungan pasien yang meningkat tidak diimbangi oleh penambahan jumlah SDM, sarana yang memadai serta ketersediaan tenaga pengganti (jika ada petugas yang sakit karena kelelahan).
Dari aspek keuangan, program KJS menimbulkan selisih antara piutang dengan realisasi pembayaran yang semakin meningkat. Tahun 2011, RSUD PR memiliki piutang sebesar Rp8,7 M dan dibayar (oleh Dinkes) sebesar Rp8,5M sehingga terdapat selisih Rp197 juta yang belum terbayar. Tahun 2012, piutang RS berjumlah Rp17,9M dan yang dibayar adalah sebesar Rp17,9M (selisih Rp1,1M). Tahun 2013 (sampai dengan Juni) piutang RS telah mencapai Rp20M dan yang telah dibayar sebesar Rp10,6M (selisih Rp9,4M). Tentunya ini mengganggu cash flow RS yang mengakibatkan RS tidak bisa membayar supplier secara tepat waktu. Dampaknya, supplier menghentikan pasokan bahan habis pakai sehingga akhirnya pelayanan jadi terganggu.
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Dr. Trinovianti melakukan upaya yang intinya adalah untuk mengendalikan mutu dan biaya. Upaya-upaya tersebut antara lain membuat clinical pathway sebagai acuan (namun diakui bahwa hal ini tidak mudah), disiplin dalam menggunakan BHP dan obat serta sosialisasi penulisan diagnosis secara lengkap untuk melengkapi rekam medis.
Harapan yang disampaikan dari perspektif pengelola pelayanan antara lain menyangkut evaluasi prgram KJS terutama dari sisi tarif, ketersediaan SDM, tarif INA-DRGs berdasarkan unit cost tiap RS/regional, jangan ada perbedaan terlalu besar antara tarif kelas bawah dengan kelas atas, penyederhanaan administrasi, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, syarat dan alur pelayanan yang harus ditingkatkan serta peran media massa untuk bekerjasama dengan RS dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut dengan informasi yang lebih detil. Selain itu juga ada saran yang disampaikan antara lain jumlah petugas verifikasi disesuaikan dengan jumlah pasien (beban kerja), pengendali dilapangan serta adanya SIM RS yang online.
Pada sesi diskusi, Prof. Dr. Sujudi mencoba memberikan pencerahan bahwa pertemuan ini harus menghasilkan solusi. Misalnya untuk mengatasi kekurangan dokter, RS bisa merekrut dokter PTT. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat DKI memiliki kemampuan anggaran yang besar. Juga perlu ada kerjasama antar-RS, misalnya dengan membuat sistem online, memanfaatkan teknologi (tele) yang didkung dengan SOP-SOP yang dimodernisasi, dan sebagainya. Prof. Sujudi juga menyarankan agar menggunakan istilah dan bahasa yang lebih sederhana dalam menjelaskan masalah ini kepada gubernur.
Terhadap pertanyaan peserta mengenai bagaimana membuat dokter spesialis mau meresepkan obat generik, pembicara menerangkan bahwa harus ada strategi yang tepat, misalnya dengan menjelaskan bahwa jika RS tidak efisien maka yang akan menjadi korban adalah jasa medis yang dipotong. Untuk mengatasi melonjaknya beban kerja dokter spesialis, triase adalah kuncinya.
 Sesi ketiga seminar pra-munas ini menghadirkan pembicara dari kalangan non-praktisi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan ada perspektif lain yang dapat didiskusikan untuk memperbaiki kondisi pelayanan di RS terkait dengan pelaksanaan kebiajakan BPJS. Pembicara yang hadir antara lain Walujani Atika (Wartawan Harian Kompas), Asep Iwan Iriawan, SH (Pakar Hukum) dan Dr. Marius Wijayakarta (Ketua YKKI).
Sesi ketiga seminar pra-munas ini menghadirkan pembicara dari kalangan non-praktisi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan ada perspektif lain yang dapat didiskusikan untuk memperbaiki kondisi pelayanan di RS terkait dengan pelaksanaan kebiajakan BPJS. Pembicara yang hadir antara lain Walujani Atika (Wartawan Harian Kompas), Asep Iwan Iriawan, SH (Pakar Hukum) dan Dr. Marius Wijayakarta (Ketua YKKI).
Atika mengaku bahwa media massa sebenarnya ikut nervous menghadapi akan berlakunya UU SJSN dan BPJS. Dia juga dpaat memahami kegamangan yang dialami oleh pelaku pelayanan kesehatan karena ini tidak hanya menyangkut perubahan administratif melainkan juga perubahan terhadap SDM dan sebagainya. Dalam hal ini ia menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap semua proses yang terjadi.
Atika mengakui bahwa sebagian pemberitaan media memang bersifat negatif. Namun demikian, ada juga pemberitaan yang positif maupun netral dalam mengadvokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, RS mengalami kekurangan infrastruktur dan dana operasional. Dilain pihak, masyarakat banyak yang kurang mampu dan meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Masalah yang dihadapi oleh RS antara lain: tidak efisien, minim dana dan masalah dalam hubungan RS-dokter, dokter-pasien dan RS-pasien serta RS-media. Ia juga mengaku tidak semua wartawan memahami masalah secara komprehensif. Yang terjadi adalah RS sibuk melayani wartawan dan wartawan membutuhkan berita. Solusi yang ditawarkan yaktu RS harus lebih komunikatif. Unit atau personal yang ditunjuk sebagai humas harus bisa menjelaskan secara detil sampai ke aspek teknis kepada masyarakat/wartawan, sehingga media tidak “mengganggu” dan menyita waktu dokter untuk memberikan penjelasan-penjelasan.
Saran Atika terhadap RS yaitu membenahi RS, transparansi pengelolaan RS, transparansi perawatan (termasuk tarif), pemahaman yang detil terhadap skema BPJS, meningkatkan kemampuan komunikasi tenaga kesehatan, internalisasi customer service pada pasien, keterbukaan informasi (misalnya dengan memanfaatkan website RS untuk informasi umum dan customer service desk untuk informasi yang lebih spesifik), meningkatkan kemampuan humas dalam memfasilitasi media dalam mendapatkan informasi, serta menyederhanakan birokrasi dalam memperoleh informasi bagi awak media (misalnya sediakan waktu untuk konferensi press jika terjadi masalah).
 Yang menarik adalah bahwa pemberitaan yang tidak proporsional dapat balas oleh RS dengan hak jawab. Ada aturan bahwa dalam menulis berita, media harus melakukan cross-check agar berita yang dipublikasi lebih obyektif. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Oleh karenanya, jika RS merasa berita yang dimuat tidak berimbang, RS dapat menggunakan hak jawab yang sama banyaknya dengan dengan luas area berita tersebut. Caranya RS bisa datang langsung ke kantor media atau menulis sendiri surat untuk dimuat di media tersebut pada edisi berikutnya. Dilain pihak, menurut Atika sebenarnya masalah tersebut dapat dibicarakan secara lebih bijak. Namun jika media yang bersangkutan “bandel”, maka dapat disomasi. Pad aumumnya hak jawab ini ditanggapi baik oleh media. Dewan pers juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan hak jawab tersebut.
Yang menarik adalah bahwa pemberitaan yang tidak proporsional dapat balas oleh RS dengan hak jawab. Ada aturan bahwa dalam menulis berita, media harus melakukan cross-check agar berita yang dipublikasi lebih obyektif. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Oleh karenanya, jika RS merasa berita yang dimuat tidak berimbang, RS dapat menggunakan hak jawab yang sama banyaknya dengan dengan luas area berita tersebut. Caranya RS bisa datang langsung ke kantor media atau menulis sendiri surat untuk dimuat di media tersebut pada edisi berikutnya. Dilain pihak, menurut Atika sebenarnya masalah tersebut dapat dibicarakan secara lebih bijak. Namun jika media yang bersangkutan “bandel”, maka dapat disomasi. Pad aumumnya hak jawab ini ditanggapi baik oleh media. Dewan pers juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan hak jawab tersebut.
Asep menekankan pada hak atas kesehatan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, RS harus waspada terhadap berbagai gugatan perdata maupun pidana yang mungkin muncul atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak ini. Dengan kata lain, RS harus benar-benar memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja sesuai dengan prosedur (standar profesi) serta sesuai dengan informasi yang diberikan pada pasien.
Marius menyoroti mengenai penilaian konsumen terhadap kinerja RS. Menurutnya, konsumen bukan raja karena posisinya sejajar dengan RS. Ia juga tidak setuju dengan istilah gratis, karena pada hakekatnya pasien miskin dibayari oleh pemerintah. Dari pengaduan yang masuk, ada sebanyak 66,7% pengaduan terhadap dokter dan 16,7% pegaduan terhadap RS. Agar menjadi lebih baik dan RS/tenaga kesehatan tidak menjadi “bulan-bulanan” masyarakat dan media, Marius menyarankan dibuatnya Standar Pelayanan Medis, yang nantinya juga bisa menjadi dasar perhitungan pembiayaan pelayanan kesehatan. Terhadap hal ini, peserta seminar menanggapi bahwa SPM ini sedang dalam proses penyusunan dan akan segera diujicobakan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Terkait dengan kisruh yang sering terjadi antara media dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, Marius mengangkat isu UU Keterbukaan dan Informasi Publik (KIP). UU ini mengatur bahwa setiap pejabat publik harus siap memberikan informasi publik, sepanjang informasi itu tidak menyangkut rahasia pasien (karena itu diatu tersendiri oleh UU lain). RS harus siap memberikan jawaban atau penjelasan, dan oleh karenanya Marius sepakat dengan Atika bahwa staf RS harus dilatih untuk itu. (pea)
[i] Konsultan dan Peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Link Terkait:











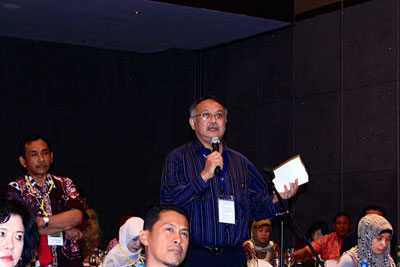






 Menurut Dr. Kuntjoro, ada tiga isu besar terkait dengan hal tersebut, yaitu mutu pelayanan, disparitas dan keaktivan RSUD dalam menyukseskan universal health coverage. Diharapkan pada tahun 2019 mutu dan biaya dapat dikendalikan. Sementara itu, ada dua hal yang dapat membantu keberhasilan pencapaian tujuan RS dalam meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat, yaitu menjadi PPK BLUD dan akreditasi. Jika telah menjalankan kedua hal ini, Dr. Kuntjoro yakin RSUD akan dicintai oleh customer-nya.
Menurut Dr. Kuntjoro, ada tiga isu besar terkait dengan hal tersebut, yaitu mutu pelayanan, disparitas dan keaktivan RSUD dalam menyukseskan universal health coverage. Diharapkan pada tahun 2019 mutu dan biaya dapat dikendalikan. Sementara itu, ada dua hal yang dapat membantu keberhasilan pencapaian tujuan RS dalam meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat, yaitu menjadi PPK BLUD dan akreditasi. Jika telah menjalankan kedua hal ini, Dr. Kuntjoro yakin RSUD akan dicintai oleh customer-nya. Munas Dibuka Secara Resmi
Munas Dibuka Secara Resmi



 Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kewajiban pemerintah yang telah dilaksanakan antara lain: telah mengalokasikan @ Rp 500M pada setiap BPJS sebagai saldo awal untuk melaksanakan kegiatan, telah mengalokasikan dana untuk PBI sebesar Rp19.225,-/jiwa/bulan untuk 86,4 juta jiwa penduduk, atau sebesar Rp19,93T untuk PBI. Selain itu pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk membayar iuran PNS, TNI, Polri, Penerima Pensiun, Veteran dan Pejuang Perintis Kemerdekaan, serta menyediakan dana untuk fasilitas pelayanan kesehatan tertentu terkait dengan fungsi Kemenham.
Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kewajiban pemerintah yang telah dilaksanakan antara lain: telah mengalokasikan @ Rp 500M pada setiap BPJS sebagai saldo awal untuk melaksanakan kegiatan, telah mengalokasikan dana untuk PBI sebesar Rp19.225,-/jiwa/bulan untuk 86,4 juta jiwa penduduk, atau sebesar Rp19,93T untuk PBI. Selain itu pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk membayar iuran PNS, TNI, Polri, Penerima Pensiun, Veteran dan Pejuang Perintis Kemerdekaan, serta menyediakan dana untuk fasilitas pelayanan kesehatan tertentu terkait dengan fungsi Kemenham. Dr. Dyah menyoroti masalah pengajuan bantuan APBN untuk pengadaan alat kesehatan di daerah. Pengajuan itu seharusnya bertujuan untuk melengkapi kekurangan ynag masih ada di daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal. Sehingga, yang diajukan adalah kekurangannya, bukan keseluruhan kebutuhan (termasuk alat yang sudah ada diajukan lagi).
Dr. Dyah menyoroti masalah pengajuan bantuan APBN untuk pengadaan alat kesehatan di daerah. Pengajuan itu seharusnya bertujuan untuk melengkapi kekurangan ynag masih ada di daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal. Sehingga, yang diajukan adalah kekurangannya, bukan keseluruhan kebutuhan (termasuk alat yang sudah ada diajukan lagi).

 Sesi pertama seminar ini diisi dengan materi-materi yang terkait dengan pengaruh tekanan pemerintah, masyarakat dan media massa terhadap pelaksanaan etika dan keselamatan pasien.
Sesi pertama seminar ini diisi dengan materi-materi yang terkait dengan pengaruh tekanan pemerintah, masyarakat dan media massa terhadap pelaksanaan etika dan keselamatan pasien. Dalam kaitannya dengan implementasi tarif berdasarkan INA-DRGs, respon yang harus dilakukan oleh RS adalah mengkalkulasi setiap biaya. Akan terjadi pergeseran jika pada mekanisme fee for service terjadi hubungan yang fokus pada dokter-pasien, dengan universal coverage hubungan ini akan bergeser ke RS-dokter, RS-pasien dan RS-media massa. Jadi RS yang akan melakukan kredensial terhadap dokter mana saja yang boleh direkrut untuk bekerja di RS tersebut. Jika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab (di pengadilan) adalah RS, bukan dokter. Di AS, pasien tidak boleh memilih dokter melainkan memilih RS.
Dalam kaitannya dengan implementasi tarif berdasarkan INA-DRGs, respon yang harus dilakukan oleh RS adalah mengkalkulasi setiap biaya. Akan terjadi pergeseran jika pada mekanisme fee for service terjadi hubungan yang fokus pada dokter-pasien, dengan universal coverage hubungan ini akan bergeser ke RS-dokter, RS-pasien dan RS-media massa. Jadi RS yang akan melakukan kredensial terhadap dokter mana saja yang boleh direkrut untuk bekerja di RS tersebut. Jika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab (di pengadilan) adalah RS, bukan dokter. Di AS, pasien tidak boleh memilih dokter melainkan memilih RS.
 Sebagai gambaran, kunjungan pasien rawat jalan sejak dilaksanakannya Program KJS meningkat hampir dua kali lipat. Sebanyak 63% dokter harus melayani lebih dari 100 pasien rawat jalan per hari dan 30% melayani 50-100 pasien per hari. Sebanyak 55% dokter menggunakan 5-6 menit waktu untuk bertemu pasien (anamnese dan sebagainya). Hanya 27% yang mengaku berbicara dengan pasien selama 30 menit. Padahal menurut Kepmenkes No. 81/2004, ada standar baku yang diatur untuk itu. Sebagai contoh, dokter spesialis penyakit dalam berdasarkan Kepmenkes tersebut harus menggunakan setidaknya 8 menit per pasien lama dan 9 menit per pasien baru di poliklinik. Alokasi waktu ini belum termasuk waktu untuk melakukan tindakan, misalnya pemasangan kateter. Ini menyebabkan 69% dokter merasa ada peningkatan beban kerja yang melebihi kewajaran dan 60% dokter merasa mudah lelah.
Sebagai gambaran, kunjungan pasien rawat jalan sejak dilaksanakannya Program KJS meningkat hampir dua kali lipat. Sebanyak 63% dokter harus melayani lebih dari 100 pasien rawat jalan per hari dan 30% melayani 50-100 pasien per hari. Sebanyak 55% dokter menggunakan 5-6 menit waktu untuk bertemu pasien (anamnese dan sebagainya). Hanya 27% yang mengaku berbicara dengan pasien selama 30 menit. Padahal menurut Kepmenkes No. 81/2004, ada standar baku yang diatur untuk itu. Sebagai contoh, dokter spesialis penyakit dalam berdasarkan Kepmenkes tersebut harus menggunakan setidaknya 8 menit per pasien lama dan 9 menit per pasien baru di poliklinik. Alokasi waktu ini belum termasuk waktu untuk melakukan tindakan, misalnya pemasangan kateter. Ini menyebabkan 69% dokter merasa ada peningkatan beban kerja yang melebihi kewajaran dan 60% dokter merasa mudah lelah.
 Pembicara selanjutnya yaitu Ahyar, SKep, NERS, MKes, yang memaparkan megenai dampak tekanan pemerintah dan media massa terhadap motivasi dan kinerja perawat. Senada dengan yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, tekanan yang muncul menyebabkan stress yang tinggi dan menurunkan motivasi serta kinerja perawat. Bahkan, pemberitaan yang tidak berimbang oleh media massa menimbulkan rasa trauma dalam melayani. Pemberitaan yang tidak imbang seringkali disebabkan oleh karena pasien tidak diberi hak sebagai pasien KJS karena tidak dapat melengkapi dokumen identitas sesuai prosedur dan kondisi kapasitas yang sudah penuh padahal ada kebijakan RS tidak boleh menolak pasien.
Pembicara selanjutnya yaitu Ahyar, SKep, NERS, MKes, yang memaparkan megenai dampak tekanan pemerintah dan media massa terhadap motivasi dan kinerja perawat. Senada dengan yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, tekanan yang muncul menyebabkan stress yang tinggi dan menurunkan motivasi serta kinerja perawat. Bahkan, pemberitaan yang tidak berimbang oleh media massa menimbulkan rasa trauma dalam melayani. Pemberitaan yang tidak imbang seringkali disebabkan oleh karena pasien tidak diberi hak sebagai pasien KJS karena tidak dapat melengkapi dokumen identitas sesuai prosedur dan kondisi kapasitas yang sudah penuh padahal ada kebijakan RS tidak boleh menolak pasien. Jumlah kunjungan pasien yang meningkat tidak diimbangi oleh penambahan jumlah SDM, sarana yang memadai serta ketersediaan tenaga pengganti (jika ada petugas yang sakit karena kelelahan).
Jumlah kunjungan pasien yang meningkat tidak diimbangi oleh penambahan jumlah SDM, sarana yang memadai serta ketersediaan tenaga pengganti (jika ada petugas yang sakit karena kelelahan).
 Yang menarik adalah bahwa pemberitaan yang tidak proporsional dapat balas oleh RS dengan hak jawab. Ada aturan bahwa dalam menulis berita, media harus melakukan cross-check agar berita yang dipublikasi lebih obyektif. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Oleh karenanya, jika RS merasa berita yang dimuat tidak berimbang, RS dapat menggunakan hak jawab yang sama banyaknya dengan dengan luas area berita tersebut. Caranya RS bisa datang langsung ke kantor media atau menulis sendiri surat untuk dimuat di media tersebut pada edisi berikutnya. Dilain pihak, menurut Atika sebenarnya masalah tersebut dapat dibicarakan secara lebih bijak. Namun jika media yang bersangkutan “bandel”, maka dapat disomasi. Pad aumumnya hak jawab ini ditanggapi baik oleh media. Dewan pers juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan hak jawab tersebut.
Yang menarik adalah bahwa pemberitaan yang tidak proporsional dapat balas oleh RS dengan hak jawab. Ada aturan bahwa dalam menulis berita, media harus melakukan cross-check agar berita yang dipublikasi lebih obyektif. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Oleh karenanya, jika RS merasa berita yang dimuat tidak berimbang, RS dapat menggunakan hak jawab yang sama banyaknya dengan dengan luas area berita tersebut. Caranya RS bisa datang langsung ke kantor media atau menulis sendiri surat untuk dimuat di media tersebut pada edisi berikutnya. Dilain pihak, menurut Atika sebenarnya masalah tersebut dapat dibicarakan secara lebih bijak. Namun jika media yang bersangkutan “bandel”, maka dapat disomasi. Pad aumumnya hak jawab ini ditanggapi baik oleh media. Dewan pers juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan hak jawab tersebut.

 Herrysan Putra, SE, Ak, dari BPKKD Prov. Kepri bahkan secara tegas menyatakan harapannya bahwa RSUD Prov. Kepri Tanjung Pinang dan RSUD Tanjunguban yang juga merupakan RS milik Provinsi Kepri dapat ditetapkan sebagai BLUD penuh tahun ini agar kinerja bisa segera ditingkatkan. Herry berharap kedua RS tersebut memiliki standar output yang sama. Oleh karena itu, dia juga meminta agar seluruh staf RS dilibatkan untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan kinerja RSUD.
Herrysan Putra, SE, Ak, dari BPKKD Prov. Kepri bahkan secara tegas menyatakan harapannya bahwa RSUD Prov. Kepri Tanjung Pinang dan RSUD Tanjunguban yang juga merupakan RS milik Provinsi Kepri dapat ditetapkan sebagai BLUD penuh tahun ini agar kinerja bisa segera ditingkatkan. Herry berharap kedua RS tersebut memiliki standar output yang sama. Oleh karena itu, dia juga meminta agar seluruh staf RS dilibatkan untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan kinerja RSUD.
 Pada acara sosialisasi ini hadir pula Wisnu Saputra, SE, narasumber dari Subdit BLUD Kementerian Dalam Negeri dan Putu Eka Andayani, SKM, MKes, narasumber dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM. Pada sesi diskusi, Wisnu menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki persepsi yang sama mengenai konsep dasar dan esensi BLUD. Masyarakat memiliki kebutuhan yang tidak dapat ditunda, yaitu pelayanan kesehatan yang tidak jarang berkaitan dengan keselamatan jiwa atau pencegahan dari kecacatan. Jika mengikuti aturan yang berlaku umum, maka instansi pemerintah tidak akan bisa memberikan layanan pada masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, muncullah berbagai regulasi setingkat UU hingga Permendagri untuk memfasilitasi instansi pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat.
Pada acara sosialisasi ini hadir pula Wisnu Saputra, SE, narasumber dari Subdit BLUD Kementerian Dalam Negeri dan Putu Eka Andayani, SKM, MKes, narasumber dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM. Pada sesi diskusi, Wisnu menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki persepsi yang sama mengenai konsep dasar dan esensi BLUD. Masyarakat memiliki kebutuhan yang tidak dapat ditunda, yaitu pelayanan kesehatan yang tidak jarang berkaitan dengan keselamatan jiwa atau pencegahan dari kecacatan. Jika mengikuti aturan yang berlaku umum, maka instansi pemerintah tidak akan bisa memberikan layanan pada masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, muncullah berbagai regulasi setingkat UU hingga Permendagri untuk memfasilitasi instansi pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Namun sering didapati bahwa RSUD disatu sisi dituntut untuk bermutu tinggi, disisi lain kebutuhan anggaran tidak dipenuhi. Padahal rencana anggaran dengan mutu sangat terkait erat. Hal ini terungkap pada penyajian Putu Eka Andayani. Putu mengatakan bahwa target pencapaian SPM harus termuat dalam RSB dan kemudian dituangkan dalam RBA. Sehingga dengan demikian, semakin tinggi target pencapaian SPM maka biasanya semakin tinggi pula anggaran yang dibutuhkan untuk mencapainya.
Namun sering didapati bahwa RSUD disatu sisi dituntut untuk bermutu tinggi, disisi lain kebutuhan anggaran tidak dipenuhi. Padahal rencana anggaran dengan mutu sangat terkait erat. Hal ini terungkap pada penyajian Putu Eka Andayani. Putu mengatakan bahwa target pencapaian SPM harus termuat dalam RSB dan kemudian dituangkan dalam RBA. Sehingga dengan demikian, semakin tinggi target pencapaian SPM maka biasanya semakin tinggi pula anggaran yang dibutuhkan untuk mencapainya.