Reportase Webinar
Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia
Rabu, 27 Februari 2020
Webinar kali ini diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Dr. Kadek Tresna Adhi, dosen dari Universitas Udayana, Bali. Kadek memaparkan hasil penelitian di Kabupaten Gianyar yang menjadi lokus stunting dan mengaitkan dengan stunting di Bali secara keseluruhan. Secara garis besar, Bali sebagai daerah yang padat dengan pariwisata telah menghasilkan kondisi ekonomi yang memadai untuk warga lokal secara umum. Dengan adanya akses pada nutrisi dan pelayanan kesehatan yang relatif mudah diperoleh, faktor yang mempengaruhi stunting di Bali berpusat pada perilaku masyarakat dan pemerintah daerah. Perilaku masyarakat yang menjadi faktor risiko terhadap stunting yang disoroti pada diskusi kali ini antara lain kebiasaan merokok seorang ayah di dekat anaknya, pemilihan makanan yang kurang mengandung tinggi vitamin A dan frekuensi kunjungan ke pelayanan kesehatan yang kurang optimal untuk pengukuran antropometri anak sebagai pemantauan pertumbuhan. Namun ada hal menarik bahwa keterlibatan ayah lebih besar dalam mengantar anak ke posyandu, sedangkan ibu lebih disibukkan oleh persiapan kegiatan upacara adat. Dari sisi pemerintah daerah, terlihat bagaimana stunting dianggap permasalahan yang hanya berpusat pada lingkup kesehatan. Tanggung jawab mengenai stunting diserahkan sepenuhnya kepada dinas kesehatan, dan kerja sama antar sektor masih belum berjalan sesuai yang diharapkan.
Diskusi dilanjutkan oleh Blandina Rosalina Bait, Senior Equity Initiative Fellow & Nutrition Officer Unicef Indonesia. Blandina menjelajah isu bukan hanya seputar stunting, melainkan juga mendiskusikan isu gizi buruk (wasting) di Indonesia, didukung oleh data dan informasi yang diperoleh di NTT. Di Indonesia, dilaporkan angka stunting pada anak melebihi 30%, yang diklasifikasikan oleh WHO sebagai angka stunting yang sangat tinggi. Tidak jauh berbeda dengan angka gizi buruk nasional, yaitu 12%, jauh melebihi target WHO sebesar <5%. Jika dilihat berdasarkan angka, terdapat sekitar 2.1 juta kasus gizi buruk dan ditemukan hanya 20.000 dari populasi tersebut yang ditangani dengan baik. Kondisi dimana angka perawatan relatif sangat rendah dibandingkan prevalensi kasus gizi buruk, dikaitkan dengan beberapa sebab antara lain buruknya skrining penyakit, fasilitas kesehatan yang tidak mampu menampung seluruh populasi yang sakit dan juga keadaan dimana pasien anak tidak di rawat inap karena orang tua memilih bekerja untuk mencari nafkah daripada menemani anak di rumah sakit.
Dalam diskusi ini dibahas pula terkait penyebab dan masalah gizi di NTT. Dari sisi individu, faktor yang menyebabkan gizi buruk dapat diakibatkan dari asupan makanan yang tidak cukup, dimana 80% anak usia 6 – 23 bulan hanya diberikan makanan bubur saja. Selain itu, ada kecenderungan untuk anak balita mengalami diare karena akses air bersih dan sanitasi buruk, ditambah lagi imunisasi dasar yang kurang lengkap sehingga menurunkan kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko infeksi. Dari sisi rumah tangga, ditemukan kemampuan daya beli rendah, dimana keluarga tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Kurangnya pengasuhan oleh seorang ibu yang meninggalkan anaknya untuk bekerja juga didapati sebagai faktor penyebab masalah gizi di NTT.
Untuk memperbaiki kondisi gizi buruk, WHO dan Unicef mengusulkan perawatan yang berbasis rawat jalan. Rekomendasi tersebut mempunyai empat komponen, antara lain mobilisasi masyarakat, penemuan penyakit dini sebelum terjadinya komplikasi, perawatan sesuai kebutuhan dan integrasi dengan layanan lain. Pendekatan tersebut sudah terbukti di berbagai negara dapat memperluas cakupan penanganan dan menurunkan mortalitas dikarenakan gizi buruk.
Gizi buruk erat kaitannya dengan stunting. Dimana gizi buruk menaikkan kemungkinan terjadi stunting dan hal tersebut dibuktikan bahwa pasien stunting sering mempunyai riwayat gizi buruk sebelumnya. DItambah lagi sosial determinan gizi buruk dan stunting yang tidak jauh berbeda. Penanganan gizi buruk dapat juga mengatasi stunting secara langsung maupun tidak langsung.
Narasumber berikutnya, Sarah Lery Mboeik, ketua kelompok pokja stunting provinsi NTT, membahas permasalahan stunting yang terjadi di NTT. Isu yang didiskusikan oleh Lery yang tidak dibahas oleh pembicara sebelumnya, adalah mengenai kesetaraan gender. Mboeik menyoroti bagaimana kurangnya prioritas yang diberikan pada kaum perempuan di NTT dapat berakibat pada stunting pada anak. Faktor resiko yang berawal dari ketidaksetaraan kaum perempuan dapat terjadi sebelum, saat, dan sesudah kehamilan. Di NTT, masih banyak kecenderungan ibu hamil dengan usia muda, dikarenakan angka perkawinan usia dini masih tinggi yang diperburuk oleh penggunaan KB yang sering dibebankan kepada kaum perempuan saja. Kehamilan pada usia muda akan meningkatkan resiko anemia, komplikasi persalinan, dan kelainan lain pada seorang ibu yang berakibat buruk pada bayi dilahirkan. Selain itu, dalam kehamilan pun jam kerja disamakan dengan orang lain dan asupan gizi tidak diperhatikan di dalah rumah tangga. Melahirkan sering dilakukan di rumah sehingga meningkatkan resiko perdarahan. Setelah melahirkan, kaum perempuan perlu untuk bekerja kembali karena kebutuhan ekonomi dan sering migrasi ke tempat yang jauh sehingga menyebabkan pengasuhan anak dititipkan ke anggota keluarga lainnya. Semua faktor tersebut berkontribusi dalam kausa stunting pada anak. Hal menarik yang dikemukakan antara lain kekerasan budaya ikut mempengaruhi ketidakberdayaan perempuan, selain itu perempuan akan mengurangi komposisi makan untuk mendukung kondisi keuangan keluarga.
Akhir kata, Digna Niken Purwaningrum, peneliti PKMK FK – KMK, menambahkan bahwa banyak penelitian yang mengaitkan status sosial ekonomi dengan stunting. Seperti yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya mengenai NTT, status sosio ekonomi yang rendah telah dibuktikan akan mempengaruhi asupan nutrisi gizi yang dapat seterusnya meningkatkan kecenderungan anak stunting. Akses pada perlindungan sosial, terutama kesejahteraan pada kelompok rentan seperti wanita dan anak, perlu diprioritaskan. Untuk mengatasi stunting perlu kerja sama dari multi sektor mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, sampai dengan evaluasi. Aksi konvergensi dari sektor kesehatan, sektor swasta, perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor terkait lainnya menjadi kunci untuk menanggulangi stunting.
Reporter : Eugeu Yasmin






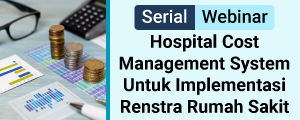


Bagus infonya tt Situasi Stunting di Bali, NTT. Menambah wacana. Tapi, saya heran banget hari gini masih ada Pemda yg pemahaman nya sangat tdk adekuat thd masalah kesehatan warganya. Sementara, kesehatan merupakan urusan wajib dan karena nya merupakan hak warga negara. Kepriben meniko ?!