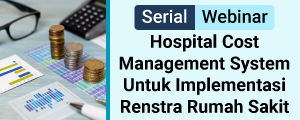Era JKN, RS Surplus atau Defisit?
Putu Eka Andayani[1]
 Semenjak diimplementasikannya Jaminan Kesehatan Nasional awal Januari lalu, setiap hari kita disuguhi berita heboh mulai dari kepesertaan, pelayanan di tingkat primer, ketersediaan obat, hingga layanan rujukan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa BPJS kurang sosialisasi sehingga pasien mengeluhkan birokrasi yang lebih rumit dibandingkan dengan era sebelum JKN dan para pemberi pelayanan mengeluhkan ketidakjelasan prosedur yang harus mereka lakukan. Tidak sedikit pula yang komplain terhadap mutu dan menyalahkan RS atas ketidakefisienan dan ketidakjelasan informasi dalam memberikan pelayanan.
Semenjak diimplementasikannya Jaminan Kesehatan Nasional awal Januari lalu, setiap hari kita disuguhi berita heboh mulai dari kepesertaan, pelayanan di tingkat primer, ketersediaan obat, hingga layanan rujukan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa BPJS kurang sosialisasi sehingga pasien mengeluhkan birokrasi yang lebih rumit dibandingkan dengan era sebelum JKN dan para pemberi pelayanan mengeluhkan ketidakjelasan prosedur yang harus mereka lakukan. Tidak sedikit pula yang komplain terhadap mutu dan menyalahkan RS atas ketidakefisienan dan ketidakjelasan informasi dalam memberikan pelayanan.
Di tengah hiruk pikuk pelaksanaan JKN tersebut, salah satu isu yang paling sering muncul adalah mengenai tarif yang oleh sebagian pihak dirasakan merugikan RS (dan pasien). Hal ini karena tarif berlaku secara paket yang sudah mencakup seluruh biaya pelayanan, padahal sebelumnya RS terbiasa dengan tarif berdasarkan jenis dan volume kegiatan. Dengan sistem paket, RS seolah-olah dibatasi dalam memberikan pelayanan sehingga mempengaruhi mutunya.
Prinsip asuransi kesehatan – apalagi asuransi sosial – memang untuk mengendalikan biaya pelayanan. Agar prinsip ini bisa berjalan, maka pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan standar kedokteran terbaik yang bisa diterima baik secara etika maupun biaya. Dengan demikian, pemberi pelayanan hanya akan melakukan tindakan yang sesuai standar, supply induced demand bisa dicegah dan para tenaga profesional bisa bekerja lebih nyaman karena bekerja menurut standar berarti terlindungi dari berbagai kemungkinan tuntutan hukum.
Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip out of pocket yang menghitung biaya berdasarkan volume tindakan atau pelayanan pada pasien. Pada kondisi ini pasien menanggung seluruh risiko biaya yang terjadi (termasuk jika terjadi tindakan atau pengobatan yang tidak perlu). Hal ini karena pasien tidak memiliki instrumen pengendali seperti yang dimiliki perusahaan asuransi atau pengelola dana jaminan kesehatan. Tidak mengherankan jika kemudian muncul istilah “Sadikin” atau sakit sedikit bisa jadi miskin. Itulah sebabnya, negara maju yang telah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya akan menggunakan asuransi (yang menggunakan sistem paket) sebagai pengendali biaya sekaligus memberikan akses pelayanan lebih luas pada masyarakat. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia menerapkan JKN untuk menuju pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
 Dari sisi pengelolaan keuangan, OOP akan memberikan kesempatan pada RS untuk memberikan jasa profesional pada staf fungsionalnya sesuai dengan kuantitas pelayanan yang mereka berikan. Semakin banyak pasien yang dilayani akan semakin banyak pula fee yang didapat. Seringkali kualitas pelayanan diabaikan, dokter tidak punya waktu untuk menjelaskan kondisi medis pada pasien hingga pasien benar-benar paham. Suatu kondisi ideal dimana dokter dan pasien menjadi satu tim untuk bersama-sama membahas penyakitnya dan memutuskan terapi yang terbaik sangat sulit terwujud. Dengan menerapkan jaminan kesehatan, pengendalian biaya dilakukan seiiring dengan pengendalian mutu pelayanan.
Dari sisi pengelolaan keuangan, OOP akan memberikan kesempatan pada RS untuk memberikan jasa profesional pada staf fungsionalnya sesuai dengan kuantitas pelayanan yang mereka berikan. Semakin banyak pasien yang dilayani akan semakin banyak pula fee yang didapat. Seringkali kualitas pelayanan diabaikan, dokter tidak punya waktu untuk menjelaskan kondisi medis pada pasien hingga pasien benar-benar paham. Suatu kondisi ideal dimana dokter dan pasien menjadi satu tim untuk bersama-sama membahas penyakitnya dan memutuskan terapi yang terbaik sangat sulit terwujud. Dengan menerapkan jaminan kesehatan, pengendalian biaya dilakukan seiiring dengan pengendalian mutu pelayanan.
Masalah terjadi ketika pelayanan menggunakan prinsip paket, namun mindset pemberi pelayanan masih pada prinsip “out of pocket”. Dengan prinsip paket, tindakan di luar prosedur akan berisiko menyebabkan terjadinya “over-budget”. Tentu saja seluruh kasus harus ada clinical path way-nya, agar sejalan dengan prinsip JKN. Namun saat ini, baru sedikit sekali kasus yang sudah ada clinical path way-nya. RS cenderung menggunakan standar lokal. Bahkan banyak RS yang belum memiliki SOP lokal sehingga menggunakan standar personal dimana antara dua dokter dalam satu RS bisa memiliki pendekatan yang berbeda. Tentu saja ini memicu biaya pelayanan yang tinggi, berlawanan dengan prinsip pengendalian biaya pada era JKN. Pada kondisi ini, tentunya RS tidak bisa berharap surplus dari pelayanan pasien BPJS. Oleh karena itu, pengembangan clinical path way masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi asosiasi profesi jika ingin memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Di sisi lain, tarif yang berlaku di RS daerah pada umumnya adalah tarif yang ditetapkan dengan Perda. Banyak sekali RS yang belum mampu menghitung unit cost sebagai dasar penghitungan tarif, sehingga tarif Perda tidak menggambarkan biaya pelayanan yang terjadi di RS. Meskipun RS mampu menghitung unit cost pelayanan, tarif Perda (untuk pelayanan kelas III) biasanya akan ditetapkan lebih rendah dari unit cost tersebut (tarif pelayanan non kelas III ditetapkan dengan SK Kepala Daerah), dengan catatan RS masih mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah untuk gaji PNS dan beberapa biaya investasi serta maintenance. Jika tarif Perda lebih rendah daripada tarif INA-CBGs, RS dengan mudah bisa mengklaim “untung”. Hal ini perlu dikaji lebih dalam apakah yang dialami oleh RS benar untung atau keuntungan semu, sebab tarif INA-CBGs sudah meliputi biaya gaji dan investasi. Perlu kehati-hatian dalam mengungkapkan hal ini, karena dapat berdampak pada kebijakan yang berlaku nasional. Jika RS melakukan penghitungan unit cost (termasuk biaya investasi dan gaji PNS) dengan benar, maka akan diketahui dengan pasti berapa sebenarnya surplus atau defisit yang dialami RS. Hal ini juga pernah diungkapkan juga oleh peneliti dari PKMK FK UGM pada seminar mengenai Reformasi Pengorganisasian RS beberapa waktu lalu.
[1] Konsultan dan Peneliti pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM