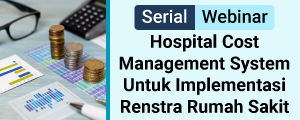Belakangan ini, isu mengenai penggunaan tenaga residen di rumah sakit pendidikan dan afiliasi RS pendidikan semakin ramai dibicarakan. Ada yang menganggap bahwa residen adalah mahasiswa atau peserta didik, sehingga “tindakannya” belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh sebagaimana tenaga kesehatan lainnya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa residen sudah menggunakan keterampilannya untuk memberikan pelayanan di RS sehingga penempatan, pemberian tanggungjawab dan haknya perlu diatur sebagai tenaga kesehatan-tenaga kesehatan lainnya.
Bagaimana sebenarnya menyikapi isu ini?
UU Praktek Kedokteran menyatakan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Berdasarkan definisi ini, maka residen (PPDS) adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Namun demikian, karena pendidikan kedokteran adalah proses yang sifatnya berjenjang, maka tingkat kompetensi yang dimiliki oleh residen yunior adalah kompetensi dasar. Semakin mendekati tahun terakhir maka logikanya kompetensi yang dimiliki sebagai dokter spesialispun akan semakin baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa residen semester akhir sudah dapat dikategorikan sebagai dokter spesialis.
Mengapa isu ini penting dibahas?
Hingga saat ini, Indonesia menghadapi masalah distribusi dokter spesialis yang sangat tidak merata. Menurut hasil penelitian terbaru PKMK FK UGM, untuk setiap 100.000 penduduk DKI Jakarta ada orang 52,75 dokter spesialis. Ini merupakan rasio tertinggi di Indonesia. Perlu diingat bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk terbanyak, sehingga jumlah dokter spesialis yang bekerja di provinsi ini juga sangat banyak. Sebaliknya, rasio terendah ada di Provinsi NTT, yaitu 1,64. Jika dilihat secara lebih spesifik pada beberapa jenis spesialisasi, maka terlihat bahwa Provinsi DKI memiliki 6,70 dokter spesialis obsgyn untuk setiap 100.000 penduduk dan NTT memiliki 0,26 dokter spesialis obsgyn per 100.000 penduduk. Dokter spesialis anak di Provinsi DKI Jakarta ada 6,42 sedangkan di Sulawesi Tenggara dan NTT hanya 0,22-0,23 per 100.000 penduduk.
Banyak provinsi tidak memiliki dokter spesialis bedah anak. Di Papua dan Sulawesi Tenggara hanya ada satu dokter spesialis patologi anatomi, sementara di DKI Jakarta ada 65 orang. Di Bengkulu hanya ada 1 orang dokter spesialis radiologi sementara di DKI Jakarta ada 182 dan di Jawa Timur ada 178 orang. Di Bengkulu dan Sulawesi Tenggara hanya ada dua orang dokter spesialis mata sedangkan di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing ada 296, 237 dan 205 orang dokter spesialis mata.
Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab tidak meratanya distribusi tenaga spesialis ini, antara lain kurangnya perekrutan tenaga di daerah dan infrastruktur minim menyebabkan sulitnya transportasi, sarana pendidikan dasar dan menengah serta berbagai pelayanan publik lainnya sangat kurang. Ini membuat banyak daerah yang belum berkembang menjadi semakin tidak menarik sebagai tempat bekerja bagi para profesional kesehatan.
Tidak meratanya dstribusi dokter spesialis ini semakin memperlebar jurang ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. RS-RS di Jawa, sebagian Sumatera dan Sulawesi memiliki jumlah yang banyak dengan jenis yang beragam, sehingga kompetensi RS-nya pun tinggi. Artinya, banyak kasus kompleks yang membutuhkan teknologi tinggi dapat ditangani oleh RS-RS tersebut. Dengan berlakunya program JKN, dana yang dikelola oleh BPJS dapat diserap dengan baik oleh daerah-daerah dengan RS yang berteknologi tinggi.
Sebaliknya, kehadiran dokter spesialis di berbagai RS pada sebagian Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua sangat minim, menyebabkan kompetensi RS rendah. Kasus sulit tidak mampu ditangani, sehingga RS hanya mampu menyerap dana JKN untuk kasu sederhana bertarif murah. Secara akumulatif, dana JKN yang berputar di daerah-daerah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju.
Memang tanggung jawab untuk memperbaiki rasio dokter spesialis ada pada pemerintah. Kemenkes sempat memiliki program flying doctor (FD) untuk melayani masyarakat di Kepulauan Seribu. Namun, sebagaimana yang pernah dibahas pada seminar “Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil” (link: http://manajemenrumahsakit.net/2014/04/seminar-pengembangan-dukungan-untuk-dokter-di-daerah-terpencil/) yang dibahas pada awal April lalu di FK UGM, Australia pun mengakui bahya flying doctor membutuhkan dana yang sangat besar. Selain itu, Indonesia memiliki 17.500 pulau besar dan kecil yang sebagian besar memiliki infrastruktur transportasi yang minim, sehingga akan dibutuhkan banyak sekali tim FD untuk bisa melayani pulau-pulau tersebut.
Strategi lain yang dimiliki oleh Kemenkes adalah program wajib kerja bagi dokter spesialis yang baru lulus. Mereka harus menghabiskan enam bulan pertamanya sebagai dokter spesialis di daerah terpencil pilihan sesuai dengan daftar yang ada di Badan PPSDM. Namun program ini hanya berlaku bagi dokter spesialis yang sebelumnya menerima bantuan pendidikan dari Badan PPSDM. Program ini pun belum bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan tenaga spesialis di berbagai daerah.
Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian. RS Pendidikan dapat memegang peranan yang lebih penting dalam mengatasi masalah ini, yaitu dengan mengembangkan “Unit Pengiriman Residen”. RS Pendidikan memiliki peserta didik yang sebenarnya merupakan tenaga kerja profesional, yaitu residen. Pendidikan dokter dan dokter spesialis berjenjang membuat peserta didik belajar sambil bekerja dan bekerja sambil belajar. Selain menimba pengalaman di RS tempatnya menempuh pendidikan, peserta didik juga perlu menimba pengalaman di RS lain dengan setting masyarakat yang berbeda, misalnya di provinsi lain. Dengan demikian, mereka memiliki pemahaman lebih baik mengenai keragaman masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Proses ini akan mendatangkan manfaat juga bagi RS yang dituju, khususnya apabila RS tersebut tidak memiliki tenaga spesialis. Misalnya peserta didik di Bagian Obsgyn RSCM, RS Dr. Soetomo, RS Dr. Sardjito dan sebagainya menjalani salah satu stasenya di NTT sekaligus untuk mengisi kekurangan dokter spesialis Obsgyn disana. Peserta didik di Bagian Mata RS Pirngadi, RS Sanglah atau RSUP Dr. Wahidin bisa mengisi kekurangan tenaga di Bengkulu dan Sulawesi Tenggara. Dan seterusnya. Daerah dapat mengalokasikan APBD untuk insentif bagi para (calon) dokter spesialis tersebut yang jumlahnya akan lebih kecil dbandingkan dengan harus merekrut dokster spesialis sendiri.
Namun program ini perlu pengelolaan yang baik dan dapat dilakukan dengan lebih efektif jika ada unit khusus yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Mengatur jadwal dan perjalanan misalnya, menjadi rumit dan memiliki risiko terjadinya miss-communication yang tinggi, jika tidak dikelola secara khusus. Oleh karenanya, RS Pendidikan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola UPR demi mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Bukan tidak mungkin suatu saat unit ini akan menjadi salah satu “core business” RS Pendidikan di Indonesia, selain pelayanan kesehatan, riset dan pendidikan tenaga kesehatan itu sendiri. (pea)