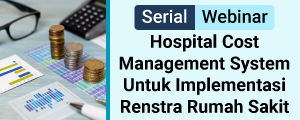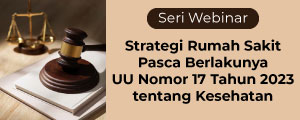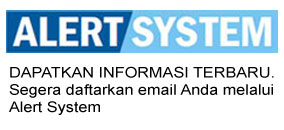Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah:
Adaptasi Terhadap Dinamika Regulasi Kesehatan Pasca-UU Nomor 17 Tahun 2023

Transformasi sektor kesehatan Indonesia telah memasuki babak baru yang ditandai dengan diterbitkannya serangkaian regulasi fundamental, menuntut adaptasi strategis yang mendalam dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), terutama rumah sakit daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan turunannya telah menciptakan kerangka hukum yang bergeser dari pendekatan sick-care menjadi health-care, sekaligus mengubah lanskap organisasi dan tata kelola kesehatan. Seiring dengan hal tersebut, kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus berevolusi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang mengamanatkan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penegasan penggunaan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG) sebagai mekanisme pembayaran klaim melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. Kombinasi dari perubahan tata kelola, pembiayaan, dan standarisasi mutu ini mengharuskan setiap rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk menyelaraskan diri secara total dengan visi jangka menengah dan panjang pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kemenkes 2025-2029 (1) dan RSB UPK Kemenkes 2025-2029 (2). Ketujuh pilar regulasi ini mulai dari landasan hukum hingga arah strategis dan pengembangan sumber daya manusia secara kolektif menempatkan kebutuhan akan Rencana Strategis yang baru dan adaptif sebagai prioritas non-negosiabel, memastikan rumah sakit daerah dapat menjaga keberlanjutan operasional, mutu layanan, dan relevansi peran dalam sistem kesehatan nasional.
Dampak paling krusial dari perubahan regulasi adalah pada aspek finansial dan operasional rumah sakit, yang wajib direspons melalui perencanaan investasi dan efisiensi yang ketat. Implementasi KRIS merupakan tantangan besar, karena standardisasi fasilitas kamar inap (seperti minimal luas, ketersediaan AC, dan kamar mandi) menuntut investasi modal (Capital Expenditure/CapEx) yang substansial, terutama bagi rumah sakit daerah yang mungkin memiliki keterbatasan anggaran atau profitabilitas (3). Transisi ini harus dihitung cermat dalam Renstra, mencakup studi kelayakan (Feasibility Study) pembiayaan CapEx dan dampaknya terhadap biaya operasional (Operational Expenditure/OpEx), mengingat tarif kapitasi KRIS yang kemungkinan akan disesuaikan. Lebih jauh lagi, sistem iDRG, yang diwajibkan oleh Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, mendorong rumah sakit untuk beralih dari fokus pada volume pelayanan menjadi fokus pada efisiensi biaya per kasus. Kegagalan dalam perencanaan strategis untuk meningkatkan akurasi koding diagnosis dan prosedur, serta optimalisasi alur klinis (clinical pathway), akan menyebabkan under-coding atau over-costing, yang secara langsung menggerus margin JKN dan mengancam keberlangsungan finansial rumah sakit (4). Perubahan pembiayaan ini membutuhkan Renstra yang berfokus pada pelatihan sumber daya manusia, penguatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk mendukung akurasi data iDRG, serta restrukturisasi unit case-mix rumah sakit.
Selanjutnya, rumah sakit daerah harus mengintegrasikan mandat pelayanan kesehatan prioritas dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terangkum dalam regulasi terbaru ke dalam peta jalan strategis mereka. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 174 Tahun 2024 tentang jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas (termasuk KJSU-KIA: Kesehatan Jantung, Stroke, Uro-nefrologi, dan Kanker) menuntut rumah sakit rujukan di daerah, bahkan rumah sakit non-rujukan, untuk menentukan peran spesialisasi mereka dan menjalin konektivitas yang jelas dengan rumah sakit pusat (5). Renstra rumah sakit harus secara eksplisit mendefinisikan kontribusi mereka pada jejaring ini, baik sebagai rumah sakit pengampu atau yang diampu, serta mengalokasikan sumber daya untuk investasi teknologi dan pengembangan kompetensi klinis yang selaras dengan spesialisasi tersebut. Seiring dengan hal itu, skema pendidikan dokter spesialis berbasis hospital-based (Residensi), sebagaimana didukung oleh UU Nomor 17 Tahun 2023, mengubah rumah sakit menjadi institusi pendidikan dan pelayanan secara simultan (6). Hal ini bukan hanya isu klinis, tetapi juga strategis; rumah sakit daerah harus merencanakan pendanaan untuk insentif pengajar, infrastruktur pendidikan, dan integrasi kurikulum, menjamin tersedianya tenaga spesialis yang kelak akan mendukung program pengampuan dan visi Renstra Kemenkes (7).
Sebagai penutup, menghadapi kompleksitas regulasi ini, Renstra yang baru harus menggunakan benchmarking global sebagai acuan untuk membangun sistem yang tangguh. Negara-negara dengan sistem Diagnosis Related Groups (DRG) yang mapan, seperti Korea Selatan, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pembayaran berbasis kasus sangat bergantung pada standarisasi layanan dan kejelasan peran rumah sakit (8). Di Korea Selatan, standarisasi mutu yang ketat memungkinkan efisiensi DRG yang tinggi, meminimalkan disparitas biaya dan menjaga kualitas. Oleh karena itu, renstra rumah sakit daerah di Indonesia harus mengadopsi pendekatan agile dan data-driven, menyerap pelajaran dari pengalaman internasional, dan memproyeksikan KRIS serta iDRG sebagai pendorong utama efisiensi, bukan sekadar beban biaya. Rumah sakit daerah harus mentransformasikan Renstra mereka dari sekadar dokumen kepatuhan menjadi instrumen manajemen strategis yang dinamis, memastikan bahwa investasi KRIS, akurasi iDRG, penguatan jejaring KJSU-KIA, dan peran dalam pendidikan spesialis (hospital-based) terintegrasi secara harmonis. Dengan demikian, Renstra menjadi kunci untuk menavigasi turbulensi regulasi, mengamankan keberlanjutan finansial, dan pada akhirnya, mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang merata sesuai cita-cita Renstra Kemenkes 2025-2029 (FFF).