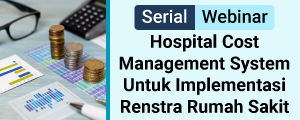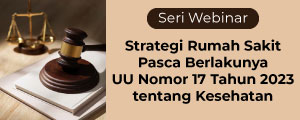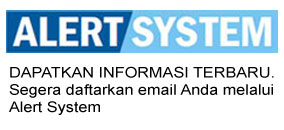Selama satu dekade lebih implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, isu yang paling sering muncul dari kalangan rumah sakit adalah “tarif INA-CBG’s yang dianggap tidak menguntungkan”. Banyak manajemen rumah sakit merasa bahwa pembayaran dari klaim JKN tidak mampu menutup biaya riil pelayanan yang mereka keluarkan. Situasi ini bukan sekadar keluhan finansial, melainkan juga menggambarkan adanya kesenjangan mendasar antara sistem tarif nasional dan realitas operasional di lapangan.
Masalahnya bukan hanya karena tarif “terlalu rendah”, tetapi karena cara tarif itu ditentukan belum sepenuhnya mencerminkan biaya sebenarnya. Sistem INA-CBG’s masih disusun berdasarkan pendekatan rata-rata nasional, bukan dari data aktual rumah sakit. Di sisi lain, banyak rumah sakit di Indonesia belum memiliki sistem akuntansi biaya yang kuat dan detail untuk menggambarkan berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan per tindakan, per pasien, atau per episode perawatan. Akibatnya, proses penetapan tarif sering kali lebih menyerupai kebijakan administratif daripada hasil dari analisis ekonomi berbasis data.
Jika kita melihat ke Inggris, situasinya berbeda. National Health Service (NHS) disana menggunakan sistem Health Resource Group (HRG), yang sepintas mirip dengan INA-CBG’s. Namun perbedaannya terletak pada pondasinya: HRG dibangun di atas sistem costing mikro tingkat pasien (Patient-Level Information and Costing System / PLICS). Setiap rumah sakit di NHS menghitung biaya riil yang dikeluarkan untuk setiap pasien, berdasarkan aktivitas klinis yang benar-benar terjadi — mulai dari waktu dokter, penggunaan ruang, obat, hingga alat kesehatan.
Data tersebut dikumpulkan secara nasional dan dijadikan dasar untuk menentukan tarif HRG yang baru setiap tahun. Dengan cara ini, tarif menjadi lebih transparan, realistis, dan berbasis bukti. Rumah sakit yang efisien dapat menjadi pembanding bagi rumah sakit lain, dan sistem pembayarannya mendorong peningkatan produktivitas tanpa mengorbankan mutu.
Untuk bisa mengarah ke sana, rumah sakit di Indonesia perlu mulai berbenah untuk mengembangkan sistem costing berbasis aktivitas dan membangun budaya/manajemen data yang lebih kuat. Artinya, menghitung biaya bukan sekadar untuk laporan keuangan, tetapi untuk memahami secara detail bagaimana sumber daya digunakan di setiap pelayanan. Sehingga diperlukan integrasi yang erat antara data klinis dan data keuangan, agar setiap tindakan medis dapat dikaitkan dengan biaya yang nyata.
Konsekuensinya tentu tidak ringan, perlu pembaruan sistem informasi rumah sakit, pelatihan staf, dan kolaborasi erat antara rumah sakit, BPJS, dan Kementerian Kesehatan. Namun hasil akhirnya akan sangat berarti. Dengan data biaya yang akurat, tarif bisa ditetapkan lebih adil, rumah sakit dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien, dan pembuat kebijakan memiliki dasar yang kuat untuk memperbarui sistem pembayaran.
Mungkin sudah saatnya Indonesia tidak lagi menyesuaikan diri dengan tarif, tetapi membangun tarif yang menyesuaikan dengan data. Oleh karena itu pada akhirnya, keberlanjutan rumah sakit bukan hanya soal besar kecilnya tarif INA-CBG’s, melainkan juga tentang sejauh mana kita memahami biaya pelayanan kesehatan secara nyata dan transparan (BWP).