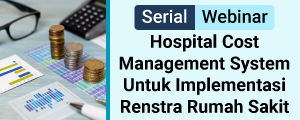REPORTASE
REFORMASI PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT
23 April 2014
Reporter:
Dr. Intan Farida Yasmin
Putu Eka Andayani, SKM, MKes
 Seminar diadakan di Fakultas Kedokteran UGM pada Rabu, 23 April 2014, dengan tema “Reformasi Pengorganisasian Rumah Sakit”. Seminar ini dihadiri oleh tim PKMK UGM, ARSADA, Litbangkes, Dinkes DIY, perwakilan dari beberapa RS Daerah, dan juga oleh para mahasiswa KMPK serta diikuti pleh para pemerhati kesehatan di seluruh Indonesia melalui streaming dan webinar. Seminar dibuka oleh Dekan FK UGM, Prof. Dr. Teguh Ariyandono Sp.B(Onk)K yang menyatakan apresiasinya kepada acara ini.
Seminar diadakan di Fakultas Kedokteran UGM pada Rabu, 23 April 2014, dengan tema “Reformasi Pengorganisasian Rumah Sakit”. Seminar ini dihadiri oleh tim PKMK UGM, ARSADA, Litbangkes, Dinkes DIY, perwakilan dari beberapa RS Daerah, dan juga oleh para mahasiswa KMPK serta diikuti pleh para pemerhati kesehatan di seluruh Indonesia melalui streaming dan webinar. Seminar dibuka oleh Dekan FK UGM, Prof. Dr. Teguh Ariyandono Sp.B(Onk)K yang menyatakan apresiasinya kepada acara ini.
RS mengalami evolusi dari PNBP menjadi Swadana dan kemudian menjadi lembaga BLU. Perubahan menjadi Lembaga BLU ini bukan berarti privatisasi (memilik otonomi penuh) melainkan korporatisasi, dengan memberikan otonomi seluruhnya atau sebagian pada beberapa aspek manajemen. Namun otonomi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, melainkan harus ada sistem pengawasan mutu pelayanan dan hukum untuk RS dikaitkan dengan tugas Dinkes dan Ditjen BUK sebagai fungsi regulator. Nantinya, diskusi-diskusi seperti ini akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan advokasi pada pemerintah. Demikian disampaikan oleh Prof. Laksono Trisnantono, MSc, PhD dalam membuka pertemuan ini.
Berdasarkan PP 38 dan 41 thn, 2007, RS bukan lembaga birokrasi dan memerlukan perizinan sama seperti RS Swasta yang berorientasi terhadap mutu dan keselamatan pasien yang tetap patuh regulasi yang ada sehingga tidak bertindak seenaknya sendiri. Regulasi yang dimaksud di sini adalah Kemenkes selaku pemerintahan pusat dan juga Pemda dan Dinas Kesehatan selaku pemberi ijin RS di daerah. Definisi pengawas RS harus diperjelas agar tidak ada dualisme fungsi. Dengan adanya penerapan sistem JKN ini, peran kuat Dinkes sebagai pengawas baik RS Pemerintah dan RS swasta diperlukan untuk menjamin setiap klaim yang diajukan benar adanya dan menghindari fraud. Hal ini menjadi sulit dengan adanya BPJS yang sebenarnya bukan lembaga kesehatan tapi seakan mengatur langsung RS Pemerintah karena BPJS membiayai pelayanan kesehatan yang dilakukan RS Pemerintah. Pada akhirnya RSD diharapkan bukan sebagai UPTD Dinkes yang mandiri dalam pengelolaan namun tetap bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan. Selain peran dari Dinkes, perlu penguatan peran Ditjen BUK sebagai pengawas eksternal RS Pemerintah.
Putu Eka Andayani, SKM, Mkes kemudian menyampaikan tentang Evaluasi Pelaksanaan BLUD: Studi Kasus di 5 RSUD. RS Daerah mengalami tantangan baru dengan adanya sistem jaminan kesehatan yang baru terutama dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang dinamis, bersaing dengan RS swasta dan RS LN serta beradaptasi dengan regulasi yang baru. Studi kasus dilakukan di 5 RS Daerah di Bantul, Yogyakarta, Sleman, Magelang, dan Banda Aceh mengenai pengelolaan RS tersebut setelah perubahan RSD menjadi BLUD. Hasil penelitiannya adalah RSD sudah mandiri dalam pengelolaan administrasi dan manajemen strategis seperti perencanaan dan penggunaan anggaran. Pengelolaan yang belum mandiri adalah SDM, pembelian dan keuangan. Studi ini juga menemukan bahwa diperlukan Dewan Pengawas (Dewas) yang bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada RSD, meskipun juga ada beberapa RSD yang merasa keberadaan Dewas masih belum efektif. Untuk kedepannya diharapkan adanya sinkronisasi antara RSD dengan Pemda setempat dan juga peningkatkan kemampuan RSD dalam penerapan kebijakan sebagai BLUD.
 Asoasiasi RS Daerah (ARSADA) Pusat yang diwakili oleh Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTPH, MKes membahas kedua materi tersebut. Menurutnya, desentralisasi menyebabkan restrukturisasi radikal di tingkat kabupaten yang perubahannya justru tidak mencapai target pencapaian, termasuk sektor kesehatan. Di tingkat mikro RS menjadi badan teknis daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Perubahan RS menjadi BLUD, menurut beliau, menyebabkan performa RS menjadi semakin kuat karena bisa beroperasi sendiri tanpa harus tergantung suplai dari pusat. Apabila RSD akan diubah menjadi UPTD di bawah Dinkes maka fungsi Dinkes sebagai provider dan regulator akan tercampur aduk sehingga good governace susah diwujudkan. Sebaiknya peran Dinkes ini diperkuat sebagai regulator dan kordinator.
Asoasiasi RS Daerah (ARSADA) Pusat yang diwakili oleh Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTPH, MKes membahas kedua materi tersebut. Menurutnya, desentralisasi menyebabkan restrukturisasi radikal di tingkat kabupaten yang perubahannya justru tidak mencapai target pencapaian, termasuk sektor kesehatan. Di tingkat mikro RS menjadi badan teknis daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Perubahan RS menjadi BLUD, menurut beliau, menyebabkan performa RS menjadi semakin kuat karena bisa beroperasi sendiri tanpa harus tergantung suplai dari pusat. Apabila RSD akan diubah menjadi UPTD di bawah Dinkes maka fungsi Dinkes sebagai provider dan regulator akan tercampur aduk sehingga good governace susah diwujudkan. Sebaiknya peran Dinkes ini diperkuat sebagai regulator dan kordinator.
Adanya pengawas untuk pelaksanaan sistem JKN di RSD juga harus diperjelas untuk menghindari fraud. Dinkes sangat diharapkan dapat berperan dalam pengawas sistem JKN di daerah. Pengelolaan RSD harus sangat efektif dan efisien agar tetap bisa memberikan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dengan anggaran yang terbatas.
Dalam sesi diskusi terdapat beberapa pertanyaan menarik dari peserta, yaitu bagaimana pengelolaan Dinkes jika RSD menjadi UPTD. Pertanyaan ini ditanggapi oleh Dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes yang juga hadir selaku Ketua ARSADA Pusat. Menurutnya, beberapa daerah merasa bahwa yang perlu dikuatkan adalah puskesmas, bukan RS. Namun dibeberapa daerah lain yang ingin dikuatkan dan diperbanyak adalah RS-nya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah membangun RS menjadi semakin mandiri dalam membayai pengelolaannya tanpa harus tergantung Pemda.
Menurut Dr. Heru Ariyadi (Sekjen ARSADA Pusat), seharusnya tidak terjadi persaingan antara RSUD dengan swasta jika regulator dan operatornya kuat. Karena kalau bersaing dengan sesama RS dalam negeri, RS tidak akan pernah bisa fokus untuk bersaing dengan RS luar negeri. Jadi tidak ada matahari kembar (Dinkes dan RSD), namun matahari dan bulan (saling melengkapi).
Drg. Agung dari RSUD Wates mengangkat kasus di RS-nya, dimana berdasarkan pada Permendagri 61/2007, Pemda boleh untuk menggunakan surplus yang berasal dari RS. Saat ini RSUD Wates hanya menerima hampir 50% gaji pegawai karena 50% lainnya adalah SDM yang direkrut sendiri oleh RS. Dari APBD RSUD Wates hanya menerima DAK 120 juta (10%), selebihnya tidak menerima apapun. Untuk investasi sebagian besar menggunakan pendapatan BLUD. RSUD yang BLUD didorong untuk rekrut SDM sendiri karena lebih mudah dikelola. Pemahaman antara Pemda sendiri masih berbeda-beda. Terkait dengan JKN, surplus tidak ada karena ada penafsiran atas dua nilai yaitu tarif INA-CBGs dan tarif PERDA. Kalimat surplus bisa bias dan menurutnya bisa membuat “perang saudara”.
Prof. Laksono menyampaikan bahwa perlu ada perhitungan yang teliti dan detail untuk perputaran keuangan RSD terutama setelah penerapan sistem JKN ini. Apakah klaim INA-CBGc termasuk dalam investasi atau penggajian atau pengoperasian? Hal ini harus diperjelas karena pendapatan RSD yang masuk ke APBD sangat tergantung pada penggunaannya dan akan sangat disayangkan jika pendapatan RSD yang masuk APBD itu malah digunakan bukan untuk pembangunan kesehatan daerah.
Tarif Perda tidak sesuai dengan tarif dari pemberi jaminan (BPJS) menurut Putu Eka, sehingga tidak mencakup biaya investasi, dan sebagainya. Menurutnya, banyak RSD memiliki tarif Perda lebih rendah dari tarif INA-CBGs sehingga seakan-akan BPJS yang memberikan subsidi ke Pemda. Dr. Kuntjoro menambahkan bahwa cara pandang Pemda yang berbeda menjadikan kegagalan regulasi RS. Pemda seharusnya mengangkat pengawas RS yang cakap dan mengerti tentang pengelolaan RS dan tidak selaiknya Kepala daerah yang menjadi pengawas RS.
 Peserta dari RS Sragen berpendapat bahwa SDM di Dinkes harus lebih menguasai tentang pengelolaan RS agar bisa meregulasi dan membina RS. Ia menambahkan bahwa harus ada kualifikasi yang jelas dari Kadinkes yang tidak tergantung dari Pemda meskipun keselarasan dari pusat dan daerah sehingga RS tetap harus dibangun. Semua ini guna menguatkan figur Dinkes agar tidak berperan sebagai kontraktor saja.
Peserta dari RS Sragen berpendapat bahwa SDM di Dinkes harus lebih menguasai tentang pengelolaan RS agar bisa meregulasi dan membina RS. Ia menambahkan bahwa harus ada kualifikasi yang jelas dari Kadinkes yang tidak tergantung dari Pemda meskipun keselarasan dari pusat dan daerah sehingga RS tetap harus dibangun. Semua ini guna menguatkan figur Dinkes agar tidak berperan sebagai kontraktor saja.
Sesi kedua seminar ini dilanjutkan oleh materi dari DR. Dra. Anastasia Susty Ambarriani, SE, AC, Ak. mengenai apakah RS akan menjadi untung dengan adanya BPJS. Opini muncul dari banyak RS pemerintah namun disangkal oleh RS swasta. Apa yang dimaksud dengan untung disini? Apakah karena tarif lebih tinggi dari tarif sebelumnya? Atau karena rekayasa/fraud? Dari data sebuah RS X, ada kesenjangan yang nyata antara klaim INA-CBGs dengan pengeluaran RS yang ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut hanya memperhitungan pengeluaran biaya langsung saja (berdasar variabel) saja sementara biaya tidak langsung seperti pemeliharaan sarana dan prasarana RS belum diperhitungkan. Hal ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi RS masih perlu dibangun untuk bisa menganalisis dengan komprehensif dalam perhitungan unit cost sehingga dapat mengitung pasti dampak penerapan INA-CBGs JKN.
Dr. Arida Utami, MKes selaku Kadinkes DIY membahas materi tersebut. Pelaksanaan JKN berdampak dalam peningkatan kualitas pelayanan medis dan juga efesiensi Rumah Sakit. Dalam menerapkan prinsip efesiensi yang harus dipenuhi adalah kesiapan SDM-nya sehingga dapat membawa keuntungan kepada RS. Sistem JKN yang terkesan ribet karena kurang kordinasi dan komunikasi antara RS – masyarakat – BPJS. Sampai saat ini Dinkes DIY belum membentuk BPRS karena kesulitan mencari SDM dengan kualifikasi pemahaman RS-penjaminan-masyarakat.
Dalam sesi diskusi kedua drg. Agung dari RSUD Wates menyampaikan bahwa RSUD Wates telah dapat menerapkan prinsip efesiensi sehingga mendapat untung yang cukup besar setelah pelaksanaan JKN. Menurutnya, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengevaluasi tarif terlebih dahulu. Jika tarif INA-CBGs hampir sama dengan tarif yang ditetapkan RS, maka “keuntungan” juga akan kecil, namun jika tarif RS lebih rendah dari tarif INA-CBGs maka keuntungan RS bisa menjadi lebih tinggi sehingga dapat lebih mandiri dalam pengoperasian harian.
Menanggapi hal tersebut, dr. Slamet mengatakan bahwa paling mudah untuk membandingkan pendapatan RS sebelum dan setelah JKN adalah dengan membandingkan pendapatan RS saat ini sebelum dan sesudah sistem JKN. Perhitungan pendapatan ini dihubungkan dengan kelompok pasien yang ditangani RS tersebut terkait dengan penerapan sistem rujukan yang sangat berjenjang pada sistem JKN.
Robert, peserta diskusi dari NTT ikut menceritakan bahwa RS di daerah perbatasan di NTT belum menjadi BLU sehingga membingungkan untuk pembayaran biaya operasional dan SDM-nya. Untuk masalah ini, dr. Arida menyarankan RS untuk bersama-sama dengan Dinkes kabupaten/provinsi mengadvokasi pemda daerah agar segera ditetapkan sebagai BLUD.
Di akhir sesi, Dra. (Apt) Selma Siahaan, MHA dari Litbangkes menyampaikan bahwa AKI tertinggi terjadi di RS berdasarkan penelitian pada tahun 2012 setelah ada penerapan Jampersal, apakah ini memang terkait mutu RS yang kurang baik? Atau ada alasan lain seperti sistem rujukan yang terlambat? Dari hasil penelitian dapat disusun rekomendasi untuk kemajuan kebijakan kesehatan. Rekomendasi tersebut antara lain adalah:
- Peningkatan infrastruktur RS baik software dan hardware
- Penguatan fungsi dinkes sebagai regulator dan kordinator
- Ada sinkronisasi pusat dengan daerah
- Sosialisasi JKN ke semua pihak yang terkait
- Ada kontrol teknis terhadap operasional RS