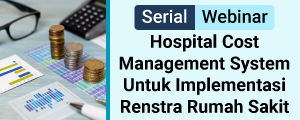Dr. Rukmono Siswihanto, M.Kes., SpOG (K) memaparkan materinya mengenai Strategi Penerapan Quality Improvement Program di RSUD
Sebagai seorang klinisi yang banyak berkecimpung dalam berbagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Dr. Rukmono Siswihanto, M.Kes., SpOG mencoba mengamati dan membandingkan angka kematian di NTT, khususnya Kabupaten Ngada dengan di DIY. Berdasarkan hasil pengamatannya, angka kematian di DIY – yang memiliki SDM dalam jumlah cukup banyak – tidak jauh berbeda dengan daerah lain (misalnya NTT) yang SDM-nya sangat terbatas. Diduga bahwa hal ini terkait juga dengan perilaku para tenaga kesehatan.
Menurut dokter spesialis Obsgyn yang juga konsultan fetomaternal di Departemen Obsgyn FK UGM ini, kematian ibu dan bayi memiliki pola yang spesifik, yaitu: 1) bersifat random dan tidak diketahui penyebabnya, 2) >80% terjadi di rumah sakit, 3) terjadi sebaran yang merata antara RS pemerintah dan RS swasta, juga tidak ada perbedaan antar-kecamatan. Namun demikian ia berpendapat bahwa AMP sangat berguna untuk mendeteksi kematian-kematian yang dapat dicegah, sehingga kedepannya dapat dikembangkan strategi untuk mendesain pelayanan agar mutunya lebih baik.
Berdasarkan hasil pengamatannya terhadap kematian ibu, ada beberapa penyebab yang selalu muncul, yaitu preeklampsi, eklampsi, perdarahan dan komplikasi medis. Pada kematian bayi, penyebab utamanya adalah asfiksia, BBLR, infeksi dan kelainan kongenital. Yang menarik adalah perbandingan penyebab kematian bayi di RSUP Dr. Sardjito (RSS) dan di RSUD Bajawa (RSB), NTT. Di RSS angka kematian bayi BBLR lebih tinggi dibandingkan dengan di RSB. Hipotesis sementaranya adalah bahwa karena prosedur di RS pendidikan, menyebabkan bayi-bayi kecil tersebut terlalu banyak mendapatkan injeksi, baik untuk pemeriksaan maupun untuk medikasi. Ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi yang berdampak pada kematian bayi. Sedangkan di RSB, karena keterbatasan peralatan, SDM dan obat-obatan, bayi dengan BBLR justru sering dibiarkan saja atau dirawat seadanya dan ternyata bayi-bayi tersebut dapat bertahan hidup.

Dr. Ekawati Lutfia Hapsari, SpA (K) dari RSUP Dr. Sardjito mendampingi dr. Rukmono dalam pemaparan materinya
Terkait dengan peralatan, menurut dr. Rukmono ada hal yang juga harus diperhatikan, misalnya keberadaan CPAP. RS memang sudah terdata memiliki CPAP, namun kuantitas juga penting untuk diperhatikan. Jika bayi bermasalah jumlahnya banyak, maka tentu dibutuhkan CPAP dalam jumlah yang juga banyak.
Dari sisi SDM, banyak perawat yang hanya terlatih untuk menangani komplikasi kebidanan, namun tidak terlatih untuk menangani komplikasi medis. Jadi jika ada ibu hamil dengan kelainan jantung, TB atau bahkan HIV-AIDS misalnya, petugas yang bersangkutan tidak dapat mengenali dan oleh karenanya tidak mampu memberikan penanganan khusus. Selain itu, petugas belum bisa bersikap netral jika ada ibu dengan kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga membuat ibu hamil tersebut justru menghindari tempat pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko kematian saat melahirkan.
Di Indonesia manual rujukan belum bisa dijalankan. Umumnya RS tidak memiliki sistem appointment khusus, sehingga pasien yang datang dari pelosok untuk mendapatkan pertolongan di RS kadangkala tidak dapat menemui dokter karena sedang mengikuti konferensi atau pelatihan di kota lain. Padahal, jumlah rujukan elektif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rujukan emergency. Dr. Rukmono mencoba mencuplik data dari Afrika, dimana rujukan sendiri jauh lebih banyak dibandingkan dengan rujukan oleh petugas kesehatan, dan rujukan persalinan lebih banyak dibandingkan dengan rujukan antenatal. Sayangnya Indonesia belum memiliki data mengenai pola rujukan ini. Agar sistem rujukan lebih efektif, menurutnya sumber daya harus diperhatikan, agar sistem rujukan tidak hanya memindahkan kematian dari primary health care atau masyarakat ke rumah sakit.

Dr. Hanevi Djasri, MARS memoderasi sesi diskusi
Hal-hal lain yang juga mempengaruhi efektifitas sistem rujukan adalah sistem komunikasi yang belum bisa dilakukan selama 24 jam, transportasi pasien dari rumah ke rumah sakit, kesepakatan protokol lokal untuk mengidentifikasi komplikasi, kerjasama tim di berbagai level rujukan, sistem pencatatan rekam medis yang tidak terintegrasi dan termonitor dengan baik, serta mekanis me untuk memastikan agar pasien tidak melakukan rujukan sendiri secara by-pass.
Banyak RS yang belum memanfaatkan AMP sebagai bagian dari proses untuk memperbaiki mutu pelayanan, melainkan hanya untuk memenuhi syarat. Padahal dengan AMP yang benar, akan dapat diketahui akar masalahnya untuk membuat solusi serta tindak lanjut (bukti adanya perbaikan).
Selain mengatasi masalah yang langsung terkait dengan rujukan pasien, RS sebenarnya juga memiliki tanggung jawab untuk membina lingkungannya, dengan melakukan counter supervision (rujukan balik ke RS lain atau puskesmas). Ini yang akan menempatkan RS sebagai center of excellent/pusat rujukan di daerahnya. RS juga dapat mengadakan seminar rutin bagi puskesmas dan RS lain disekitarnya, dengan anggaran yang berasal dari APBD (RS maupun dinas kesehatan). Selain menjadi sumber pembelajaran klinis, RS juga dapat menjadi sumber pembelajaran manajemen bagi puskesmas, misalnya mengenai pengelolaan obat-obatan.
Dalam kesempatan ini, dr. Rukmono juga menekankan bahwa RS memiliki peran sentral di daerahnya yaitu adekuasi sumber daya dan meningkatnya komplikasi medis sebagai penyebab kematian maternal. Untuk itu diperlukan peran kepemimpinan dari direktur untuk membuat dokter spesialis obsgyn, anak dan anestesi berada pada satu tim yang solid. Sebagai Pembina jejaring rujukan, RS juga harus mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis bukti untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa peran profesi terkait dengan 6 rekomendasi untuk RS, yaitu adekuasi sumber daya, peran spesialis diluar Obsgyn, Pembina jejaring rujukan, perbaikan proses internal RS, implementasi pelayanan berbasis bukti untuk mengatasi pemborosan. Menurutnya, masih banyak pihak di hampir seluruh sektor yang belum benar-benar memahami perannya masing-masing.